Banyak orang mengenalnya sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia dalam pemberontakan 1926 dan 1948. Yang pertama aksi PKI menentang pemerintah kolonial Belanda. Yang terakhir gerakan PKI di Madiun, Jawa Timur, melawan pemerintah pusat.
Dialah Musso, anak Kediri yang ketika kecil dikenal rajin mengaji. Mendapat pendidikan politik ketika indekos di rumah H.O.S. Tjokroaminoto, di masa-masa awal kemerdekaan sepak terjangnya tak bisa diremehkan. Peran politik Musso bisa disejajarkan dengan peran Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka.
Dia belajar politik di Moskow, Rusia, dan mengamati dari dekat strategi gerakan komunis Eropa. Ia bermimpi tentang negeri yang adil, setara, dan merdeka seratus persen. Ia memilih jalan radikal, bersimpang jalan dengan kalangan nonkomunis, bahkan juga kalangan kiri yang tak segaris. Tapi radikalisme itu tak membuatnya bertahan. Ia lumat dalam gerakan yang masih berupa benih. Akhir Oktober, 62 tahun lampau, Musso tersungkur.
Radikal Kiri Si Bocah Alim
Musso berasal dari keluarga berada buat ukuran zamannya. Lahir dengan nama Munawar Muso pada 1897, ia tumbuh di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Musso bersama Sidik, adiknya, hidup berkecukupan. Ayahnya, Mas Martoredjo, pegawai kantoran pada bank di Kecamatan Wates, tak jauh dari rumah. Ibunya bekerja di rumah, mengelola kebun kelapa dan kebun mangga.
Di desa terpencil itu, Musso tumbuh bersama dua teman karib: Ronodihardjo dan seorang lagi yang belakangan dikenal sebagai Kiai Kemendung. Mereka bocah alim yang rajin ke Musala Ar-Rahman milik Ki Demang Telo, ayah Ronodihardjo. Ki Demang Telo ketat menjaga ibadah mereka. Ia tinggal hanya 50 meter dari rumah orang tua Musso. “Ke mana-mana selalu bersama,” kata Agus Pitono, 47 tahun, cucu Ronodihardjo, yang memperoleh cerita dari kakeknya.
Menurut Agus, Musso dan Ronodihardjo mengendarai sepeda motor kebo-merek Ural buatan Soviet. Masuk akal, karena orang tua mereka cukup kaya. Orang tua Ronodihardjo memiliki sepertiga tanah di Desa Jagung. Adapun keluarga Musso menguasai banyak tanah, termasuk di beberapa desa lain. Luas tanah di sekeliling rumah orang tua Musso saja tiga hektare. Di sana berdiri satu bangunan rumah dan ratusan pohon kelapa.
Agus mengatakan ibu dan neneknya menggambarkan Musso sebagai orang yang pintar berorganisasi. Perkawanan Musso, Ronodihardjo, dan Kiai Kemendung putus ketika Musso melanjutkan sekolah ke kota pada usia 16 tahun. Ronodihardjo mewarisi jabatan ayahnya, demang. Sedangkan Kiai Kemendung mendirikan pondok pesantren di Dusun Kemendung, Desa Jagung. Itulah sebabnya masyarakat menyebut dia Kiai Kemendung.
Tiap kali Musso menjenguk orang tuanya, tiga bersahabat itu selalu berkumpul. Hanya, belakangan Kiai Kemendung jarang bergabung karena sibuk di pondok. “Tinggal Kakek dan Mbah Musso. Seperti saudara kandung,” kata Agus.
Kini sepetak tanah kosong di Desa Jagung menjadi saksi bisu lahirnya Musso, pentolan Partai Komunis Indonesia. Rumah besar gaya priayi Jawa yang dulu berdiri megah di situ tak ada bekasnya. Rumah itu sudah dibongkar puluhan tahun lalu. Hanya rerumputan dan perdu yang tumbuh. Tanah itu kini milik Erny, 55 tahun. Ia bukan kerabat Musso.
Erny membeli tanah ini dari Sidik. Rumah dan tanah sekitar tiga hektare milik orang tua Musso belakangan menjadi milik Sidik. Pada 1970-an, Sidik memecah tanah jadi sembilan petak dan menjualnya. Saat itu harga tanah Rp 50 ribu per ru-satuan luas setara 1 x 14,5 meter. “Mbah Sidik pindah ke dekat penjara Mojoroto,” kata Erny, tiga pekan lalu. Mojoroto adalah kecamatan dalam wilayah Kota Kediri. Tapi jejak Sidik tak ditemukan.
Sekitar 200 meter dari rumah itu, Nyatin, 80 tahun, yang pernah menjadi pembantu rumah tangga orang tua Musso, membuka warung kopi. Tapi Nyatin tak mau dikorek banyak soal keluarga Musso. Ia pernah didatangi orang yang mengaku intelijen. Itulah sebabnya Nyatin memilih mengubur dalam-dalam kisah kedekatannya dengan keluarga Musso. “Saya takut,” kata dia, tiga pekan lalu.
Menurut Ruth T. McVey dalam The Rise of Indonesian Communism, yang diterbitkan Cornell University Press, Ithaca, New York, pada 1965, Musso menempuh sekolah guru di Batavia atau Jakarta. Di sekolah ini, ia bertemu dengan Alimin, yang kelak juga menjadi pentolan gerakan kiri Indonesia. Musso adalah anak didik pertama G.A.J. Hazeu, penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan bumiputra. Hazeu pula yang mengangkat Alimin sebagai anak. Hazeu pertama kali berjumpa dengan Alimin sebagai bocah gembel di alun-alun Solo. Hazeu memberi dia beberapa keping uang dan Alimin langsung membagi rata kepada temannya. Hazeu terkesima oleh Alimin kecil yang punya bibit sosialisme.
Di sekolah itu, Musso berguru pada seorang reformis politis etis, D. Van Hinloopen Labberton, yang juga Ketua Theosofische Vereeniging di Batavia. Madjallah Merdeka terbitan Oktober 1948 seperti dikutip McVey menyebutkan, setelah tamat pendidikan guru di Batavia, Musso kuliah di kampus pertanian di Buitenzorg atau Bogor. Kampus ini cikal-bakal Institut Pertanian Bogor.
Versi lain menyatakan Musso bersekolah di Hogere Burger School. Soemarsono, pemimpin militer gerakan Madiun 1948, menyebutkan Musso dua tingkat lebih senior dibanding Sukarno, yang masuk HBS Surabaya pada 1915. Di Surabaya, Musso kos di rumah tokoh pergerakan Tjokroaminoto. HBS adalah sekolah lanjutan menengah untuk orang Belanda, Eropa, atau elite pribumi.
Sekolah ini berpengantar bahasa Belanda dan ditempuh lima tahun. Bekas gedung HBS Surabaya kini adalah Kantor Pos Besar Kebonrojo, sekitar 300 meter dari rumah Tjokroaminoto di Peneleh. Arnold C. Brackman dalam Indonesian Communism terbitan 1963 mengatakan Musso bekerja sebagai kasir kantor pos Surabaya. Di sini, Musso berhasil mengorganisasi buruh kantor pos. “Musso juga punya reputasi sebagai jagoan jalanan Surabaya,” kata Brackman.
Buku H.O.S. Tjokroaminoto, Hidup dan Perdjuangannja, terbitan Partai Sarekat Islam, yang dikutip McVey, menyebutkan rumah Tjokroaminoto tempat penting bertemunya secara pribadi pemimpin pergerakan. Asrama ini dikelola Suharsikin, istri Tjokroaminoto, pada 1913-1921. Di sini, Musso, Alimin, dan Sukarno berguru pada Tjokroaminoto. Ketika Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam pada 1912, Musso juga aktif di pergerakan itu. Rumah Tjokroaminoto menjadi pusat kegiatan Sarekat Islam.
Di rumah Tjokroaminoto ini, Musso bertemu dengan Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet, yang suka pada ide-ide sosial demokrat revolusioner. Sneevliet datang ke Hindia Belanda (Indonesia) pada 1913. Ia menetap di Surabaya selama dua bulan dan menjadi Pemimpin Redaksi Handelsblad. Selama di Surabaya, Sneevliet kerap berdiskusi dengan murid-murid Tjokroaminoto, termasuk Musso. Musso bersama Alimin, Semaoen, Darsono, Mas Marco Kartodikromo, dan Haji Misbach menjadi kader Sneevliet. Setahun kemudian, Sneevliet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), yang berhaluan Marxisme.
Sneevliet pula yang memasukkan gagasan sosialis dalam tubuh Sarekat Islam melalui Musso-Alimin dan lainnya. Sneevliet jeli melihat Sarekat Islam sebagai organisasi rakyat yang memiliki basis massa besar. Itu sebabnya Sneevliet masuk dan menanamkan pengaruhnya dengan membangun blok merah di Sarekat Islam. Apalagi Sneevliet adalah orang yang berani menyuarakan gagasan “Hindia Belanda Merdeka”-gagasan yang revolusioner untuk masa itu ketika Belanda kuat menancapkan imperialisme.
Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan mewawancarai Darsono, kawan pribadi Musso, pada 1964. Menurut Darsono, Musso adalah orang yang senang amuk-amukan karena ikut gerakan Sarekat Islam Afdeling-B. Sarekat Islam Afdeling-B atau Seksi B atau Sarekat Islam B adalah suatu cabang revolusioner. Gerakan ini didirikan oleh Sosrokardono pada 1917 di Cimareme, Garut, Jawa Barat.
Menurut sejarawan Ricklefs, selain menangkap Sosrokardono, Belanda menangkap Musso dan Alimin. Mereka adalah orang ISDV yang disusupkan ke Sarekat Islam. Selama di penjara, Musso mendapat perlakuan buruk. Meski begitu, sikap revolusioner dia tak langsung tampak setelah bebas dari penjara. Menurut Soe Hok Gie, perlakuan menyakitkan itulah yang membuat Musso makin benci kepada Belanda. Di penjara ini pula Musso intens bertemu dengan kawan-kawan komunis. “Di sana, Musso mendapat political lesson tentang komunisme secara intensif,” kata Soe Hok Gie.
McVey menyatakan Van Hinloopen Labberton berencana menjadikan Musso asisten mengajar di Jepang. Tapi pemerintah Jepang menyatakan Musso tak memenuhi syarat. Ia dianggap tak mampu mengajarkan bahasa Indonesia menggunakan pengantar bahasa Inggris. Padahal Musso menguasai dua bahasa ini dengan baik. McVey curiga itu lebih karena faktor Musso yang beraliran politik radikal. Apalagi dia pernah dipenjara.
Segera setelah penolakan Jepang itu, Musso mengumumkan berdirinya Partai Komunis Indonesia cabang Batavia. Semaoen mendirikan Perserikatan Komunis Hindia yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1920. Musso dan Alimin bergabung dengan Partai Komunis Indonesia pada 1923.
Rumah bercat putih di Jalan Peneleh VII Nomor 29dan 31, Surabaya, itu memiliki model paling lawas dibandingkan dengan para tetangga. Sejak 1870, arsitektur rumah tersebut tak pernah diubah. Warga sekitar mengenal tempat tinggal peninggalan Haji Oemar Said Tjokroaminoto itu sebagai rumah kos Sukarno, sang proklamator.
Rumah kos sekaligus sebuah tempat kursus politik Sukarno muda. “Orang di sini tahu hanya Bung Karno yang pernah tinggal di rumah itu. Kalau yang lain-lain kami tidak pernah mendapat cerita dari orang-orang tua kami,” kata Mariyun, salah seorang warga asli di gang itu. Namun Bung Karno hanya satu di antara sederet nama penting penghuni rumah tersebut: Musso, Alimin, Semaoen, dan Kartosoewirjo.
Bekerja sama dengan sang istri, Suharsikin, Tjokroaminoto-ketika itu menjabat Wakil Ketua Sarekat Islam cabang Surabaya-menampung sekitar 30 pemuda Indonesia dengan biaya ringan. Sukarno bersekolah di Hogere Burger School (HBS) Regenstraat, Surabaya. HBS setingkat sekolah lanjutan tingkat menengah dengan masa pendidikan lima tahun. Sukarno mulai mondok sejak umur 14 tahun, sepanjang 1915-1920.
Musso memiliki tempat khusus di hati Sukarno. Mereka bertukar pendapat di mana saja, kapan saja. Sembari makan bersama, misalnya, Musso berbagi pikiran tentang penjajahan Belanda yang membuat, “Kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa,” kata Sukarno dalam Sukarno an Autobiography karya Cindy Adams.
Saat itu, menurut Ketua Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru, Sumaun Oetomo, 87 tahun, Musso telah menyelesaikan pendidikan di Batavia dan telah menjadi aktivis di Sarekat Islam dan ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Musso aktif dalam gerakan yang sama bersama Alimin, Semaoen, dan Darsono. Musso lebih tua empat tahun dibanding Sukarno, yang lahir pada 1901.
Berdasarkan penelusuran literatur, tak ada penjelasan berapa lama Musso tinggal di rumah Tjokroaminoto. Yang jelas, pada 1919, Musso tak menghuni rumah itu lagi. Menurut Ruth McVey dalam The Rise of Indonesian Communism, pada tahun itu Musso dan Alimin terlibat kasus Sarekat Islam Afdeling-B di Jawa Barat dan dijebloskan ke penjara. Keluar dari penjara itulah, pada 1920 Musso menjadi anggota Partai Komunis Indonesia-penerus warisan ISDV.
Berpisah selama hampir tiga dasawarsa, Sukarno dan Musso bertemu lagi pada 13 Agustus 1948 pukul 10 pagi di Istana Negara. Musso menyamar sebagai Soeparto, sekretaris Soeripno-dubes RI untuk Cekoslovakia di masa Amir Sjarifoeddin. Dalam bukunya Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Soe Hok Gie melukiskan betapa mengharukan pertemuan itu. “Bung Karno memeluk Musso dan Musso memeluk Sukarno. Kegembiraan ketika itu rupanya tidak dapat mereka keluarkan dengan kata-kata. Hanya pandangan mata dan roman muka mereka menggambarkan kegembiraan itu,” demikian kesaksian Soepeno, pemimpin redaksi surat kabar Revolusioner, yang hadir dalam pertemuan itu, seperti dikutip Soe Hok Gie.
Dengan bangga Bung Karno bercerita kepada Soeripno tentang masa lalunya dengan Musso. “Musso ini dari dulu memang jago. Ia yang paling suka berkelahi. Ia jago pencak,” kata Sukarno. Sukarno juga bercerita tentang hobi Musso bermain musik dan bila berpidato akan menyingsingkan lengan baju.
Sukarno pun menyindir soal perkembangan politik komunis internasional. Pengetahuan Sukarno tentang komunis sempat membuat Musso ternganga. Bung Karno menjawab keheranan Musso dengan pengakuannya, “Saya ini kan masih tetap muridnya Marx, Pak Tjokroaminoto, dan Pak Musso!”
Sukarno menunjukkan kekiriannya dengan memperlihatkan buku karangannya, Sarinah. Dalam buku itu, Sukarno mengutip ucapan-ucapan Lenin dan Stalin. Buku itu diberikan kepada Musso sebagai tanda mata.
Tiga puluh tujuh hari setelah pertemuan itu, pecah Peristiwa Madiun. Keduanya saling memaki. Meski begitu, rasa hormat Sukarno kepada Musso sebagai guru tak luntur. Dalam wawancara dengan Cindy Adams, Sukarno berkata, “Ajaran Jawa mengatakan, seseorang yang menjadi guru kita harus dihormati lebih dari orang tua.”
Pengkhianatan di Singapura
Menyamar sebagai Matros, Musso tiba di Singapura pada awal 1926. Tak ada petugas yang mengenali tokoh penting Partai Komunis Indonesia itu. Rute pelayaran Sumatera-Singapura-Malaka yang amat ramai, dan keahlian Musso memalsukan dokumen, memudahkan pria kelahiran Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur, pada 1897, itu menyusup masuk.
Musso dan Alimin sebetulnya pernah ditahan di Singapura, tapi kemudian dilepaskan. “Pemerintah Singapura hanya memperhatikan orang yang masuk ke Malaka dengan cara ilegal,” kata sejarawan Harry Poeze kepada Tempo di Yogyakarta pekan lalu.
Musso, Budisutjitro, dan Sugono ketika itu sedang menjadi buron pemerintah kolonial Belanda. Di Singapura, ketiga buron ini bertemu dengan Alimin dan Subakat, anggota PKI yang juga sedang diburu polisi Belanda.
Mereka mematangkan rencana pemberontakan yang dijadwalkan pada medio 1926. Rapat itu kelanjutan pertemuan rahasia di Prambanan, Jawa Tengah, Desember 1925. Pada rapat kilat itu, para pemimpin PKI di bawah Sardjono memutuskan akan melakukan pemogokan yang diikuti pemberontakan bersenjata.
Gerakan akan dimulai di Padang, Sumatera Barat-cabang PKI paling kuat. Ruth T. McVey dalam The Rise of Indonesian Communism mencatat mereka mendirikan organisasi rahasia bernama “Organisasi Diktatorial” untuk memimpin partai, dan “Organisasi Kembar” untuk mempersiapkan pemberontakan. Sugono, Ketua Serikat Buruh Kereta Api (VSTP), diam-diam meragukan rencana pemberontakan itu. Dia tahu ikatan buruh masih lemah sehingga tak mungkin melakukan pemogokan umum.
Ketika Musso dan kawan-kawan tiba di Singapura, Tan Malaka justru telah meninggalkan negeri bandar itu, dan tinggal di Manila, Filipina. Musso mengutus Alimin untuk menemui Tan Malaka-yang menjadi wakil Komunis Internasional di Asia Tenggara.
Dalam buku Pergulatan Menuju Republik: Tan Malaka, Harry Poeze menduga pemimpin komunis berwibawa yang sedang menderita penyakit tuberkulosis ini tengah mencari perlindungan dari kawan-kawannya di Filipina. Di sana, Tan sudah mengetahui rencana pemberontakan melalui surat pengurus PKI tertanggal 16 Desember 1925.
Dalam surat itu, pengurus PKI meminta Tan Malaka menjadi perantara untuk meminta dukungan Moskow. Membaca surat itu, Tan terkejut. Ia termasuk orang yang taktis dan selalu berhati-hati. Pada 4 Januari 1926, ia mengirim surat balasan yang menolak rencana pemberontakan itu.
Soe Hok Gie, dalam buku Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, menyatakan lima faktor yang menyebabkan Tan Malaka menentang putusan Prambanan. Antara lain: belum ada situasi revolusioner, tingkat disiplin PKI masih rendah, seluruh rakyat belum berada di bawah PKI, belum ada tuntutan yang konkret, dan imperialisme internasional sedang bersekutu melawan komunisme.
Mulanya, Budisutjitro dan Subakat juga akan menemui Tan Malaka di Manila. Tapi, begitu membaca surat balasan Tan, mereka mengurungkan niat. Mereka memutuskan menunggu kedatangan Tan dan Alimin ke Singapura untuk sebuah konferensi. Musso geram abis membaca surat penolakan itu. Dari sinilah berawal perseteruan Musso dan Tan Malaka.
“Menurut Tan Malaka, rencana aksi tidak matang,” kata Poeze. “Musso dan Alimin punya pikiran pendek.” Perbandingan kekuatan kolonial dan PKI juga sangat tidak seimbang. Lantaran kurang sehat, Tan Malaka tak datang ke Singapura. Alimin kembali pulang sendirian. Harry Poeze menyatakan Tan Malaka hanya menitipkan risalah penolakan keputusan Prambanan. Dia menilai keputusan itu tanpa pertimbangan matang, dan beberapa pemimpin PKI tidak mempunyai wewenang mengorganisasi pemberontakan tanpa persetujuan Moskow.
Di bangsal kebun pepaya milik Ki Masduki di Geylang Serai, pinggiran Singapura, Alimin menemui para pemimpin PKI yang sedang buron itu: Sardjono, Budisutjitro, Sugono, Winanta, Musso, Subakat, dan Agam Putih, yang menanti dengan tak sabar. Namun, dalam rapat itu, Alimin tak menyampaikan lengkap alasan penolakan Tan Malaka.
Poeze menduga Alimin sengaja menutupi sikap Tan, agar rencana pemberontakan tetap berjalan, dan ia bisa dikirim ke Moskow sebagai utusan PKI. Dalam buku Sedjarah PKI, Djamaluddin Tamim menulis, ketika di Manila, tiga kali Alimin bertanya kepada Tan Malaka kapan ia dikirim ke Moskow.
“Risalah itu tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah dibacakan oleh Alimin,” kata Poeze. “Ia hanya bilang Tan Malaka setuju, padahal tidak.” Sebaliknya, Alimin melapor kepada Tan Malaka bahwa risalah sudah disampaikan, tapi ditolak pemimpin PKI yang lain.
Pada medio Maret 1926, Musso dan Alimin berangkat ke Moskow, dengan lebih dulu singgah ke Kanton, Cina. Mereka pergi tanpa sepengetahuan Tan Malaka. Tak pernah ada pertemuan antara Musso dan Tan Malaka.
Lantaran tak mendapat kabar apa-apa dari Singapura, Tan Malaka mengirim laporan tentang keputusan Prambanan dan pendapatnya atas rencana pemberontakan itu kepada Komintern. Surat Alimin baru tiba dua bulan kemudian, yang menyatakan konferensi di Singapura batal serta memberitahukan rencana kepergiannya ke Moskow.
Membaca surat itu, “Tan Malaka merasa Alimin menipunya,” kata Poeze.
Setelah itu, Tan Malaka bergegas ke Singapura untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiba di sana, pada Juni 1926, Tan hanya bertemu dengan Subakat dan Agam Putih. Alimin dan Musso sudah berangkat ke Moskow, dan pemimpin lainnya balik ke Indonesia. “Dia mendapat informasi risalah itu tidak pernah dibicarakan oleh Alimin,” kata Poeze. Tan Malaka merasa dikhianati oleh Alimin dan Musso.
Kepada Subakat, Tan Malaka menyampaikan alasan penolakannya. Pada medio Juni, Subakat menulis surat kepada para pemimpin PKI agar mau bertemu dengan Tan Malaka di Singapura. Suprodjo, sebagai Ketua PKI, langsung datang ke Singapura. Tan Malaka, Subakat, dan Suprodjo sepakat membatalkan keputusan Prambanan.
Pada awal Juli, Suprodjo membawa hasil kesepakatan itu ke Indonesia. Namun sejumlah pemimpin PKI berniat tetap meneruskan pemberontakan, meski hanya empat cabang yang ikut, yaitu Batavia, Banten, Priangan, dan Sumatera Barat. Pemberontakan seharusnya dilaksanakan pada Mei-Juni, tapi mundur dari jadwal.
Budisutjitro dan Tamim ingin aksi tetap berlanjut, tapi ragu-ragu karena tidak semua cabang PKI siap. Tamim berangkat ke Singapura pada akhir Juni 1926 menemui Subakat dan mencari Alimin-Musso. Secara tak terduga dia malah bertemu dengan Tan Malaka. Awalnya, Tamin sangat yakin akan rencana pemberontakan, tapi akhirnya mengalah juga oleh argumen Tan Malaka.
Di Moskow, Musso menjegal Tan Malaka. “Ini sejarah yang pedih dan peran Musso tidak begitu baik,” kata Poeze. “Ini pengkhianatan kawan separtai.” Kelompok Tan Malaka melakukan berbagai upaya untuk mencegah rencana pemberontakan. Di Jawa, para pemimpin PKI yang nekat meneruskan keputusan Prambanan pun mulai melihat tanda-tanda amburadulnya organisasi cabang dan sulitnya menggalang dana.
Pemberontakan tetap meletus pada 12 November 1926 di Jawa Barat, seperti Batavia dan Banten, lalu pada Januari 1927 di Silungkang, Sumatera Barat. Belanda dengan cepat bisa menguasai keadaan. Hanya dalam beberapa pekan, keamanan pulih. Orang-orang komunis ditangkapi, dan tiga tokoh pemberontakan di Jawa Barat-Egom, Hasan, dan Dirdja-dihukum gantung.
Tan Malaka dan pendukungnya hanya bisa menyaksikan tragedi itu tanpa daya. Alimin dan Musso tak diketahui rimbanya. Mereka baru kembali ke Singapura pada pengujung 1926. Keduanya memang telah berpesan kepada para pemimpin PKI: disetujui atau tidak oleh Moskow, pemberontakan harus tetap berjalan.
Bung Hatta, dalam memoarnya yang diterbitkan oleh Tintamas, menulis: “Alimin dan Musso pergi ke Moskow mencari persetujuan. Tapi mendengar laporan itu, Stalin marah dan tak setuju, serta meminta pembatalan rencana pemberontakan.” Hatta mendengar cerita itu dari Semaoen, yang singgah di Den Haag setelah mengunjungi Moskow.
Soe Hok Gie menulis, akibat pemberontakan PKI 1926, tak hanya PKI yang dibubarkan. Pecahnya PKI mempengaruhi mundurnya gerakan kaum kiri di Indonesia. Poeze menambahkan, “Kalau ada gerakan kiri yang bersatu, Indonesia yang sosialis akan lebih besar waktu revolusi.”
Bangkit Setelah Mati Suri
Polisi bernama Ahmad dan Sanusi mengetuk pintu rumah Tribudi-bukan nama sebenarnya-di Candi, Semarang, sekitar pukul dua dinihari. “Zus, Zus, cepat bangun. Sekarang juga kita berangkat,” kata mereka kepada ibu Tribudi. Sang ibu segera bersiap, dan bersama ketiga anaknya, termasuk Tribudi yang masih bayi merah, segera menuju kapal Kruiser Java di pelabuhan Semarang. Ayah Tribudi dan banyak orang lain telah menunggu di sana.
Sekitar dua pekan kemudian, tepatnya 23 Maret 1927, rombongan interniran-orang buangan-ini tiba di Tanah Merah, Boven Digul, Papua. Di sana, menurut Tribudi, mereka dibawa ke barak-barak yang sudah dihuni oleh rombongan interniran gelombang pertama. “Rombongan Pak Ali Archam dan kawan-kawan,” tulis pria 84 tahun ini kepada Tempo lewat surat elektronik.
Ribuan tokoh dan pendukung Partai Komunis Indonesia dibuang ke Boven Digul akibat pemberontakan yang mereka lakukan pada 1926-1927. Setelah periode bergejolak itu, PKI tercerai-berai. Buku The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia karya Guy J. Pauker menyebutkan, pasca pemberontakan, sekitar 13 ribu orang ditangkap, 5.000 ditahan untuk mencegah kembali terjadinya huru-hara, 4.500 dipenjara, dan 1.308 dibuang ke Digul. PKI dinyatakan ilegal pada 1927. Partai pun sekarat. Apalagi, sebelumnya, sudah banyak petingginya yang dibuang, ditahan, atau dipaksa meninggalkan Indonesia.
Soe Hok Gie dalam buku Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan menyebutkan Ali Archam dibuang ke Digul pada 1925. Tan Malaka sudah dipaksa pergi tiga tahun sebelumnya. Haji Misbach meninggal pada 1926 setelah dua tahun hidup di pembuangan. Alimin pun telah lari.
Belanda berusaha menangkap Musso pada Januari 1926. Tapi ia berhasil lolos ke Singapura, bergabung dengan Alimin, Subakat, Sanusi, dan Winata. Setelah insiden 1926, Musso berlabuh ke Rusia, Semaoen ditugasi ke Tajikistan, dan Alimin mengembara sebagai petugas Komunis Internasional (Komintern) di Cina.
PKI memang mati suri, tapi usaha menghidupkannya kembali tetap dilakukan. Dalam tulisan Soetopo Soetanto di buku Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis disebutkan, di Bangkok, Tan Malaka membentuk Partai Republik Indonesia, meski akhirnya gagal.
Di Belanda, Semaoen mendatangi Mohammad Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia. PKI dan Perhimpunan membuat konvensi. Isinya antara lain Perhimpunan Indonesia mengambil kepemimpinan dan bertanggung jawab penuh atas gerakan rakyat Indonesia, PKI harus mengakui kepemimpinan Perhimpunan, dan percetakan di bawah PKI harus diserahkan ke Perhimpunan. Tapi, karena tekanan Komintern, konvensi tersebut dibatalkan setahun kemudian, 19 Desember 1927.
Pada saat bersamaan, kader PKI seperti Abdulmadjid berusaha merekrut simpatisan, di antaranya Setiadjid, Rustam Effendi, Sidartawan, Maroeto Daroesman, Gondopratomo, dan Jusuf Muda Dalam. Ketika fasisme mulai mengoyak dunia, dan Jerman menduduki Belanda, kaum komunis Indonesia tersebut-bersama aktivis lain-ikut dalam gerakan bawah tanah. Saat itu, Moskow menetapkan kebijakan baru dengan membentuk front yang menyatukan kaum komunis, sosialis, dan borjuis yang dinamai Garis Dimitrov. Mahasiswa komunis Indonesia di Belanda tidak lagi menuntut “kemerdekaan sekarang juga”.
Di Digul, menurut Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, keadaan juga kacau. Sebagian orang buangan di bawah Gondojuwono bekerja sama dengan Belanda. Yang tetap keras, termasuk Ketua Umum PKI Sardjono, diasingkan ke tempat yang lebih terpencil, ke Gudang Arang, kemudian ke Tanah Tinggi.
Pada 1937, ketika berdatangan orang buangan dari grup PKI Muda atau PKI 1935, seperti Hardjono, Djoko Soedjono, dan Achmad Sumadi, warga buangan di Digul mendapat angin baru. Garis baru Komintern: bekerja sama dengan kaum borjuis dan kolonialis untuk melawan fasis serta memperkuat keyakinan kelompok yang menghalalkan kerja sama dengan Belanda. Mereka pun membentuk Komite Antifasis, yang menyatakan setia ke Hindia Belanda, dan bersedia dipersenjatai untuk melawan kekuatan fasis. Namun taktik itu gagal karena pasukan Jepang keburu menjejak pintu gerbang Digul. Para interniran tersebut diangkut ke Australia.
Di Negeri Kanguru, mereka membuka kontak dengan Partai Komunis Australia dan membentuk PKI di pengasingan dengan Komite Pusat di Brisbane. Penggeraknya adalah Ngadiman, Djoko Soedjono, dan Sabariman. PKI baru ini juga meminta Sardjono, yang tinggal di Melbourne, membentuk PKI Sibar (Serikat Indonesia Baru). Mereka bekerja sama dengan Belanda.
Kelompok yang menentang keputusan Komintern 1935 mendirikan Partai Kebangsaan Indonesia, yang tetap berslogan “Indonesia merdeka sekarang juga”. Sedangkan di Jawa, sebelum 1935, tak ada peristiwa luar biasa di tubuh PKI. Aktivis komunis yang tersisa bersembunyi atau bergabung dengan organisasi lain.
Ketika Moskow memutuskan kebijakan baru dengan menetapkan Garis Dimitrov, Musso kembali ke Indonesia dan membentuk PKI Muda atau PKI 1935. Pengurusnya adalah Pamudji, Sukajat, Djoko Soedjono, Achmad Sumadi, Sutrisno, Sukindar, dan Soehadi. Tapi kemudian pemimpin PKI Muda juga ditangkapi dan dibuang ke Digul. Pamudji, yang sempat lolos, bergerak di bawah tanah. Sebagian pendukung PKI lain bergabung dengan Gerakan Rakyat Antifasis. Ada juga yang kemudian tergabung dalam Gerindo dan Partai Sosialis Indonesia.
Apalagi saat itu sudah ada Garis Dimitrov yang mengizinkan kaum komunis bekerja sama dengan kaum nasionalis dan kolonialis. Banyak orang komunis bekerja sama dengan politikus non-PKI dan Belanda, termasuk Amir Sjarifoeddin. Dalam buku Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis, Soetopo Soetanto menyebutkan Amir menerima tawaran Van der Plas membentuk jaringan bawah tanah untuk melawan Jepang. Ia pun diberi US$ 10 ribu untuk mendanai gerakannya.
Mantan Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat-salah satu organisasi di bawah PKI-Jawa Tengah, Hersri Setiawan, membenarkan kisah tersebut. “Karena itulah PKI disebut sebagai PKI Van der Plas,” katanya. Karena aktivitas bawah tanahnya, pada 1944, Amir bersama ratusan orang lain, termasuk Pamudji, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Namun Amir terselamatkan dengan campur tangan Sukarno-Hatta.
PKI mati suri. Baru setelah deklarasi kemerdekaan, para aktivis komunis kembali muncul terang-terangan. Pada 21 Oktober 1945, Mohammad Jusuf menghidupkan kembali PKI. Namun, pada Maret 1946, ia memberontak untuk mendirikan Republik Indonesia Soviet. Menurut Harry Poeze dalam The Cold War in Indonesia, 1948, Panitia Pemberesan (Purgation Committee) kemudian mengumumkan PKI Jusuf bukan penerus PKI 1926.
Pada saat bersamaan, para tetua komunis dari negeri seberang pulang ke Tanah Air. Pada Maret 1946, kelompok Digul datang dari Australia, disusul para mahasiswa dari Belanda, yang dikenal sebagai kelompok PKI intelektual, seperti Setiadjid, Abdulmadjid, dan Maroeto Daroesman. Pada Agustus, Alimin juga datang.
Tan Malaka telah pulang pada Januari sebelumnya. Ia langsung membentuk Persatuan Perjuangan yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Saat itu, kebanyakan pendatang bersikap moderat. Menurut Hersri, PKI dari sayap Belanda dan Digul membentuk satu kelompok. “Mereka ingin meneruskan garis Partai Komunis Belanda, membentuk commonwealth,” katanya.
Amir Sjarifoeddin pun tetap menjalankan Garis Dimitrov. Dia kemudian menduduki jabatan perdana menteri, merangkap menteri pertahanan. Namun, ketika muncul kebijakan baru yang dideklarasikan saat pembentukan Communist Information Bureau (Cominform), yakni Garis Zhdanov, pada September 1947, era kompromi dan kerja sama dengan kaum nasionalis dan kolonialis pun putus.
PKI melakukan revisi. Semua kebijakan lama disalahkan, termasuk penandatanganan Perjanjian Renville oleh Amir Sjarifoeddin dan penyerahan kekuasaannya. “Ia sampai diadili teman-temannya sendiri,” kata tokoh Pemuda Sosialis Indonesia yang juga salah satu pemimpin insiden Madiun, Soemarsono. Kedatangan Musso pada Agustus 1948 kian mengeraskan PKI. Musso pun memulai kampanye konsep baru, “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.
Bersuara di Rusia
Musso kembali ke Moskow pada 1927, setelah berhasil lolos dari pengejaran tentara kolonial Belanda. Beberapa bulan sebelumnya, Musso memang pernah ke Moskow guna meminta persetujuan untuk memberontak melawan Belanda. Di negara tempat dia berkiblat, Musso menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan Partai Komunis Soviet bersama kawan Alimin dan Semaoen. Sekitar sepekan sekali, ia mengisi siaran berbahasa Indonesia di radio pemerintah. Jangkauan radio ini memang tidak mencapai Indonesia. Siarannya lebih ditujukan ke mahasiswa dan aktivis Indonesia yang saat itu banyak berada di sana.
Musso juga masuk ke struktur partai dan menjadi staf urusan Indonesia. Lewat penerbitan komunis internasional bernama Inprekorr, singkatan bahasa Jerman untuk “korespondensi pers internasional”, ia menyerang Tan Malaka. Menggunakan nama alias Krause dalam artikel yang menyoal Trotskyisme di Indonesia, ia menuding Tan sebagai pengkhianat bangsa dan layak dibunuh. Ini masih berhubungan dengan konflik keduanya mengenai pemberontakan 1926 yang dilibas Belanda. Lewat artikel satu halaman berhuruf kecil yang tersusun dua kolom itu, Musso melabeli Tan sebagai pengikut Trotsky, lawan politik Joseph Stalin, pemimpin utama Partai Komunis Soviet, yang menjadi kiblat komunisme internasional.
Karier Musso kembali moncer berkat keikutsertaannya dalam Kongres Komunis Internasional (Komintern) ke-6, yang digelar di Moskow pada Juli 1928. Joseph Vissarionovich Stalin, yang saat itu baru empat tahun memimpin Soviet dan sedang giat mengukuhkan kekuasaannya, memimpin langsung kongres tersebut.
Stalin mendeklarasikan tujuan utama komunisme, yaitu menciptakan sistem komunis dunia yang berada dalam kontrol Rusia. Ia menggunakan kesempatan ini untuk mengecam perlawanan Sun Yat Sen dan Mahatma Gandhi dalam mengusir penjajah Barat. Keduanya disebut sebagai nasionalis borjuis. Namun Stalin menutup mulut rapat-rapat terhadap petualangan Musso dan Alimin dalam usaha mendongkel Belanda. Ini ditafsirkan sebagian orang sebagai restu Stalin terhadap gerakan komunis Musso.
Kongres Komunis Internasional ke-6 ini, selain oleh Musso, diikuti oleh Alimin, Semaoen, Darsono, dan Tadjudin sebagai utusan Tan Malaka. Musso menggunakan nama samaran Manavar, Semaun dengan nama K. Samin, Alimin memakai nama Animin, dan Tadjudin beralias Alphonso. Musso memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan penyebab tumpasnya pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatera pada 1926. Menurut dia, pemberontakan gagal akibat pertikaian parah di antara pimpinan partai.
Seusai kongres, Musso didapuk sebagai anggota Komite Eksekutif Komunis Internasional. Ia juga sempat mengikuti pendidikan di sebuah universitas di Moskow, tetapi berhenti di tengah jalan karena sibuk mengurusi partai. Misalnya, Musso sempat berkunjung ke Vladivostok, yang terletak di sebelah timur Rusia. Di sana ia menggunakan nama samaran Sidin atau Sheegin untuk menghindari penciuman intelijen Barat.
Dalam perjalanannya kembali ke Indonesia dari Moskow, pada sekitar awal 1948, Musso mampir ke Belgia dan Prancis. Di dua negara itu ia berhubungan dengan para pemimpin komunis setempat. Ia sempat ditahan aparat dan dijebloskan ke penjara. Di Prancis ia menemui Maurice Thorez, seorang pemimpin komunis setempat.
Ia juga sempat ke Belanda dan berbicara panjang lebar dengan Paul de Groot, pimpinan Communistische Partij Nederland. De Groot dan Musso terlibat perdebatan panas mengenai perlu-tidaknya Indonesia tetap dalam persemakmuran di bawah Belanda jika merdeka. De Groot akhirnya mengalah dan menerima desakan Musso agar Partai Komunis Belanda mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun De Groot hanya memberinya sedikit uang untuk ongkos pulang ke Indonesia.
Kaum Merah Dari Bawah Tanah
Suatu siang April 1935. Siti Larang Djojopanatas, aktivis perempuan progresif di Surabaya, diminta menemui seorang tamu rahasia di Hotel Simpang, hotel terkenal di kota itu. Penghubungnya bernama Pamudji, pemimpin koran Indonesia Berdjoeang.
Siti Larang bergegas berangkat. Ketika itu, baru setahun berlalu setelah Siti kehilangan suaminya, Sosrokardono. Sosro adalah tokoh PKI senior yang dipenjara pemerintah kolonial Belanda pada 1919 dengan tuduhan menggerakkan pemberontakan Sarekat Islam di Afdeling-B di sekitar Garut, Jawa Barat. Dua tokoh PKI, Musso dan Alimin, ketika itu juga dibui dengan dakwaan yang sama.
Tak disangka-sangka, tamu rahasia yang menunggu Siti adalah Musso. Pemimpin PKI yang lari ke Moskow, Rusia, pascapemberontakan 1926 itu ternyata diam-diam sudah menyusup masuk ke Indonesia.
Siti Larang adalah salah satu orang pertama yang dicari Musso sekembalinya ke Tanah Air. Selain dekat dengan suaminya, Sosrokardono, Musso sudah mengenal Siti sejak bersama-sama menumpang hidup di rumah Ketua Sarekat Islam H.O.S. Tjokroaminoto.
“Saya perlu dicarikan rumah kontrakan untuk beberapa bulan,” kata Musso, begitu mereka bersua, seperti dikutip dari catatan obituari saat Siti meninggal September 1998. Dalam pertemuan itu, Musso banyak bercerita soal ancaman kekuatan fasisme di Eropa dan Asia. Perkembangan baru ini tentu menuntut strategi baru kaum komunis.
Di Moskow, angin perubahan memang tengah berembus. Pada awal 1935, Georgi Dimitrov terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Komunis Internasional. Dialah yang berperan mengubah taktik perjuangan kaum komunis. Dari semula berkeras memerangi imperialis, mereka kini mulai mengulurkan tangan kepada golongan kapitalis dan borjuis nasional.
Tak hanya itu. Dimitrov juga mengeluarkan instruksi agar anggota-anggota Komintern di wilayah jajahan mulai bekerja sama dengan penguasa kolonialnya untuk menghambat gerak maju kaum fasis. Soe Hok Gie dalam bukunya, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, menyebut Musso sebagai agen Komintern yang mendapat mandat untuk menjelaskan garis baru itu di Indonesia.
Pada pertemuannya dengan Siti Larang, Musso mengaku akan segera “mendirikan front demokrasi antifasis di sejumlah kota”. Tampak jelas Musso ingin memanfaatkan perubahan taktik perlawanan Komintern untuk membangkitkan kembali PKI di Indonesia.
Langkah pertama Musso ketika itu adalah mempublikasikan Garis Dimitrov di sejumlah surat kabar lokal. Koran Indonesia Berdjoeang, yang dipimpin Pamudji, termasuk yang getol memuat artikel Musso. “Dia menulis tiga artikel soal ini,” kata Sumaun Oetomo, Ketua Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru.
Karena itulah Pamudji dipercaya Musso menjadi salah satu pemimpin Komite Sentral PKI baru. Musso juga merekrut Azis, Sukajat, dan Djoko Soedjono. Mereka berlima menjadi ujung tombak upaya aktivis komunis mengkonsolidasikan kembali kekuatannya. “Fokus Musso ketika itu adalah Surabaya dan Solo, Jawa Tengah,” kata Hersri Setiawan, mantan Ketua Lekra Jawa Tengah.
Selama enam bulan-sumber lain menyebut satu tahun-di Indonesia, Musso aktif berkeliling dan memberikan ceramah. “Tapi semuanya dilakukan secara rahasia,” kata Sumaun. Kuatnya jejaring dinas intelijen Belanda, Politieke Inlichtingen Dienst, membuat gerak-gerik kaum kiri di Tanah Air saat itu amat sempit. Tak sedikit aktivis komunis yang ditangkap sebelum sempat melakukan apa pun. Pamudji bahkan dihukum mati.
Dalam kondisi terjepit itu, Musso berhasil menarik Amir Sjarifoeddin dan Tan Ling Djie masuk PKI. “Musso dikenalkan pada Amir melalui anggota Perhimpunan Indonesia yang kiri,” kata Sumaun. Lapis pertama kader Musso di Surabaya ini juga berhasil melantik puluhan pemuda, termasuk Sudisman dan Soemarsono, menjadi kader merah.
Mereka inilah yang kemudian berperan besar dalam aksi-aksi sabotase anti Jepang pada periode 1942-1945. Namun, sesuai dengan instruksi Musso saat itu, semua aksi mereka dilakukan tanpa bendera palu-arit. “Itulah kesalahan strategi besar PKI: terlambat muncul dari bawah tanah,” kata pentolan Pemuda Sosialis Indonesia, Soemarsono.
Kembalinya Sang Komunis Tua
Pesawat amfibi Catalina itu mendarat di rawa-rawa Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 Agustus 1948. Pada masa itu, rawa-rawa luas di dekat bendungan Niyama itu memang sering menjadi titik pendaratan pesawat yang membawa tamu-tamu rahasia untuk Republik.
Dua pria beriringan keluar dari pesawat. Seorang pria belia berperawakan tinggi ramping ditemani seorang pria setengah baya bertubuh gempal dengan wajah keras. Yang lebih muda bernama Soeripno, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Praha, Cekoslovakia. Adapun pria di belakangnya mengaku bernama Soeparto, sekretaris pribadi Soeripno.
Di tepi rawa-rawa, sebuah mobil menanti. Menurut sejarawan Belanda, Harry Poeze, mobil penjemput hari itu adalah milik pentolan Pemuda Sosialis Indonesia, Soemadi Partoredjo. Seperti dikutip dari buku Poeze, Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949, mobil itu dipilih karena kondisi keempat bannya yang masih baik.
Tak lama berbasa-basi, rombongan segera melaju pergi. Mereka mengarah ke Solo, Jawa Tengah. Di sana, Gubernur Militer Wikana-seorang tokoh Partai Komunis Indonesia terpandang-sudah bersiap menyambut dua tamu dari jauh itu.
Tak banyak yang sadar bahwa kedatangan dua orang dari Praha ini akan membawa konsekuensi politik yang amat besar untuk perjalanan sejarah Republik Indonesia muda, beberapa pekan berikutnya.
Pria setengah baya yang mengaku sebagai “sekretaris” itu sebenarnya adalah Musso, 50 tahun, tokoh legendaris PKI yang ikut mencetuskan pemberontakan para buruh pada 1926. Setelah lebih dari 20 tahun bermukim di Moskow, Rusia, pada medio 1948 itu dia memutuskan sudah saatnya kembali ke Indonesia.
Moskow, Januari 1948, delapan bulan sebelum kepulangan Musso. Perjanjian Renville baru saja ditandatangani di Indonesia. Pemimpin Partai Komunis Uni Soviet bergegas meminta sebuah laporan dibuat mengenai kondisi terakhir gerakan komunis di Nusantara.
Analisis itu dinilai penting karena, setahun sebelumnya, Moskow baru merilis garis perjuangan baru yang lazim dikenal sebagai doktrin Andrei Zhdanov. Berdasarkan teori ini, kaum komunis dianjurkan “mulai mengambil jarak dari kubu imperialis yang dimotori Amerika Serikat”. Tindakan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin-pemimpin koalisi sayap kiri di kabinet Indonesia, yang menandatangani pakta Renville di atas kapal Amerika yang berlabuh di Tanjung Priok-menimbulkan tanda tanya di Moskow.
Musso segera menyusun laporan. Namun minimnya informasi tangan pertama membuat analisisnya tidak akurat. Kepada pemimpin Partai Komunis Uni Soviet, Musso membela tindakan Amir dan kameradnya di Indonesia. Dia menyebutnya sebagai “taktik saja, untuk tidak menarik perhatian kaum antikomunis”. Musso bahkan menjamin posisi kelompok kiri dalam militer Indonesia masih cukup kuat.
Dalam hitungan hari, analisis Musso terbantah habis. Pada 23 Januari 1948, sepekan setelah Renville ditandatangani, Amir Sjarifoeddin dipaksa mundur dari kursi perdana menteri. Posisi politik dua rival blok kiri, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia, juga menguat.
Kesalahan laporan Musso segera dikritik hebat. Sejarawan Rusia, Larissa Efimova, mengutip laporan dua analis Rusia, Kogan dan Luhlov, menuding Musso “berkhayal” dan “membenarkan sebuah strategi yang membawa malapetaka”.
Kepala Divisi Asia Tenggara di Departemen Kebijakan Luar Negeri Komisi Sentral Partai Komunis di Uni Soviet, Plishevsky, mengirim surat ke Politbiro dan menegaskan bahwa “taktik keliru PKI telah menyebabkan berpindahnya kekuasaan di Indonesia kepada partai-partai kanan”.
Meski tak pernah ada dokumen yang menegaskan adanya tugas resmi dari Moskow kepada Musso, dalam bukunya, Dari Moskow ke Madiun?, Larissa menyebut Musso “merenungkan cukup lama kritik Partai Komunis Uni Soviet atas taktik lama PKI” sebelum akhirnya menetapkan diri untuk mengambil peran sentral meluruskan garis perjuangan partainya.
Pada April 1948, Musso meninggalkan Moskow, menuju Praha, Cekoslovakia. Di sana, dia mengaku bernama Musin Makar Ivanovich, dan menyamar menjadi sekretaris pribadi Soeripno, pejabat Indonesia setingkat duta besar yang ditempatkan Menteri Luar Negeri Agus Salim di sana sejak medio 1947.
Pada pekan ketiga Mei 1948, Soeripno berhasil membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Keberhasilan Soeripno ini disambut pro-kontra-sebagian menilai hubungan diplomatik resmi dengan Soviet bisa mendorong Republik jauh ke kiri. Tak sampai sepekan kemudian, sebuah kawat resmi dikirim ke Praha: Soeripno dipanggil pulang ke Yogyakarta. Sekretaris pribadinya, Musin Ivanovich alias Musso, ikut pulang ke Indonesia.
Selama enam minggu di perjalanan-dari Praha, lewat Kairo, New Delhi, berhenti sebentar di Bangkok lalu Bukittinggi-Musso terus merahasiakan identitasnya. Menurut catatan Harry Poeze, dia bahkan berkeras tidak mau difoto. “Setiap kali ada kamera mengarah kepadanya, Musso selalu memalingkan muka, atau menyembunyikan wajah di balik koran atau buku.”
Namun di Solo, kedatangan tokoh sekaliber Musso tak bisa lagi disembunyikan. Sambutan Wikana yang demikian hangat kepada “Soeparto” membangkitkan kecurigaan.
Pada 12 Agustus, dua hari setelah kedatangannya, berita pertama soal kepulangan Musso muncul di harian Merdeka, Solo. Pada berita berjudul “Soeparto al Musso” dijelaskan bahwa “ada kemungkinan, tokoh kawakan Musso yang sangat terkenal itu telah kembali”.
Berita kecil itu segera disusul kabar-kabar selanjutnya di media lain. Dua media prokomunis, Suara Ibukota dan majalah Revolusioner-keduanya terbit di Yogyakarta-bahkan mempublikasikan wawancara panjang dengan Musso, selama tiga hari berturut-turut. Salah satu redaktur koran Suara Ibukota adalah Wikana.
Dalam artikel itu, Musso dengan panjang-lebar menjelaskan pentingnya pembentukan sebuah pemerintahan front nasional. “Tujuan tunggal dari mobilisasi seluruh potensi kekuatan kita dalam sebuah front nasional adalah memerangi pemerintah kolonial Belanda,” kata Musso, seperti dikutip jurnalis harian Rakjat, Soerjono, dalam catatannya untuk sejarawan Amerika, Ben Anderson.
Sehari kemudian, Musso menemui Presiden Sukarno di gedung Agung, Yogyakarta. Mereka berpelukan lama. “Lho, kok masih awet muda?” tanya Bung Karno sambil tersenyum lebar. Musso menjawab tangkas, “Oh ya, ini semangat Moskow. Semangat Moskow selamanya muda.”
Setelah bercakap-cakap panjang, di akhir pertemuan, Sukarno mengajak Musso membantu meredakan pertikaian antarkelompok dalam tubuh Republik. Seperti dicatat wartawan Revolusioner, Soepeno, Presiden berujar takzim, “Saya harap Pak Musso, setelah kembali ke Tanah Air, bisa membantu menciptakan rust en orde.” Musso menjawab dalam bahasa Belanda, “Ik kom hier om orde te scheppen (Saya memang datang ke sini untuk menciptakan ketertiban).”
Meniti Jalan Radikal
Diskusi tiga tokoh komunis itu berlangsung alot. Hari itu, pada suatu siang Maret 1948, Paul de Groot, Musso, dan Soeripno bertemu di Praha, Cekoslovakia. De Groot merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda. Adapun dua nama terakhir tokoh komunis Indonesia.
Pertemuan itu dilakukan untuk merumuskan strategi baru gerakan komunis Indonesia. De Groot, dalam pertemuan itu, menghendaki Indonesia tetap menganut garis front rakyat yang lebih kooperatif. Adapun lawan diskusinya tak sependapat. Musso ingin komunis Indonesia memakai garis perjuangan radikal. Ia menolak gagasan rekannya dari Belanda itu, yang dinilai terlalu “lembek”.
Diskusi juga melebar ke soal status hubungan Indonesia-Belanda. De Groot ingin hubungan dua negeri ini dalam kerangka persemakmuran, sedangkan Musso menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Jalan tengah akhirnya dicapai. Disepakati Belanda akan diberi keleluasaan di bidang ekonomi dan kebudayaan.
Pertemuan ini akhirnya merumuskan garis besar arah pergerakan kaum komunis Indonesia. Ditandatangani wakil Indonesia, Belanda, dan Cekoslovakia, dokumen itu lantas dikirim ke Moskow untuk mendapat persetujuan. Haluan baru inilah yang kemudian dibawa Musso dan Soeripno, yang saat itu menjabat Duta Besar RI di Cekoslovakia, ke Tanah Air pada Agustus 1948. Menurut Himawan Soetanto, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata RI, dalam bukunya Rebut Kembali Madiun, haluan ini dipengaruhi “garis Zhdanov”.
Musso menyempurnakan rumusan ini dalam perjalanan dari Praha ke Indonesia, yang memakan waktu seminggu. Rumusan itu ia sebut “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Jalan Baru inilah yang kelak mengubah politik komunis di Indonesia. “Saya harap kawan-kawan di Indonesia akan mengerti dan bersedia mengikuti,” demikian tulis Musso seperti dikutip sejarawan Belanda, Harry Poeze, dari tulisan Soeripno.
Musso menyebut “Jalan Baru” karena gagasannya itu berbeda dengan haluan komunis sebelumnya. Sejak 1935, komunis Indonesia, kata Himawan, menganut garis Dimitrov. Georgi Dimitrov adalah Sekretaris Jenderal Komunis Internasional. Dimitrov menganjurkan komunis bekerja sama dengan kaum liberal kapitalis demi menghadang ancaman fasisme dan Naziisme. Garis Dimitrov bersifat lunak dan kooperatif.
Komunis Indonesia pun kemudian menempuh garis lunak: berunding dan berkompromi dengan Belanda, yang pemerintahannya dikuasai partai kiri. Demikian pula saat menghadapi penjajahan Jepang yang fasis. Meski bergerak di bawah tanah, kaum komunis masih bekerja sama dengan Belanda.
Namun, setelah Amerika mulai membendung laju komunis Eropa lewat Marshall Plan, Uni Soviet mengubah kebijakannya: bergeser ke garis keras. Garis ini mengadopsi pemikiran Andrei Alexandrovich Zhdanov, petinggi Partai Komunis Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Perubahan haluan ini dideklarasikan oleh Communist Information Bureau (Cominform) pada September 1947, dan tahun berikutnya disampaikan dalam Konferensi Pemuda se-Asia Tenggara di Calcutta, India.
Haluan ini menegaskan, dunia telah terbelah dalam dua blok: kapitalis imperialis yang dimotori Amerika Serikat dan blok anti-imperialisme yang dimotori Uni Soviet. Inti doktrin Zhdanov, menurut Soe Hok Gie dalam bukunya, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, kerja sama dengan kaum imperialis tidak perlu dilanjutkan dan partai-partai komunis harus mengambil garis keras. Musso dalam rumusan “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” menyatakan, “Karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, Indonesia satu garis dengan Rusia.”
Pulang ke Indonesia, Musso, yang saat itu memakai nama samaran Soeparto untuk mengelabui Belanda, menghubungi dua koleganya, Maroeto Daroesman dan Setiadjid, untuk bertukar pikiran. Saat itu dua tokoh komunis ini juga baru kembali dari Belanda bersama rombongan Menteri Kehakiman Mr Soewandi, yang baru berunding dengan Belanda.
Musso pertama kali menjabarkan gagasan Jalan Barunya pada pertemuan Politbiro, 13-14 Agustus 1948, di Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, Musso mengkritik sejumlah kelemahan dan kesalahan perjalanan organisasi komunis di Indonesia setelah kepergiannya ke Moskow. “Menurut Musso, revolusi di Indonesia bukan revolusi proletariat, melainkan revolusi borjuis, sehingga harus ada front yang dipimpin orang-orang proletariat,” ujar Hersri Setiawan, penulis Negara Madiun: Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan.
Melalui surat kabar, Musso juga mengkritik keras kesalahan-kesalahan mendasar revolusi nasional yang digelorakan Sukarno. Ia mempersoalkan antara lain tidak adanya wakil kelas buruh dalam pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjalankan politik revolusioner. Demikian juga kekuatan bersenjata. Menurut dia, angkatan bersenjata seharusnya adalah tentara rakyat yang benar-benar dibangun dari dan untuk rakyat.
Menakhodai strategi Jalan Baru, langkah pertama yang dilakukan Musso adalah mengambil alih pimpinan Front Demokrasi Rakyat dan melebur Partai Komunis, Partai Buruh, dan Partai Sosialis serta Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) menjadi partai tunggal, Partai Komunis Indonesia. Semua pemimpin organisasi tersebut oleh Musso diminta bersumpah menentang politik pemerintah.
Sesuai dengan doktrin organisasi, Musso meminta para pemimpin organisasi melakukan otokritik. Salah satu buah otokritik itu, belakangan, adalah terungkapnya pengakuan Amir Sjarifoeddin yang menerima 25 ribu gulden dari Van der Plas, petinggi Belanda yang juga Gubernur Jawa Timur di era Republik Indonesia Serikat. Musso juga mengkritik tindakan Amir yang membubarkan kabinetnya. Menurut Musso, melepaskan sebuah kekuasaan yang telah berada di tangan merupakan kesalahan besar.
Kebijakan komunis yang juga dipersalahkan Musso adalah perkembangan partai komunis ilegal yang dibentuknya pada 1935 untuk melawan fasisme Jepang. Setelah Proklamasi, di mata Musso, partai ini tidak segera mengubah diri mengikuti perkembangan politik yang terjadi.
Menurut Musso, adanya tiga partai yang sama-sama berorientasi pada buruh, yakni “PKI legal”, Partai Buruh Indonesia (PBI), serta Partai Sosialis yang dikendalikan oleh PKI ilegal, dan sama-sama berdasarkan Leninisme dan Marxisme, telah membuat keruwetan organisasi. Ini justru menghalangi perkembangan organisasi kelas buruh. Lantaran banyak kelemahan itulah Politbiro memutuskan melakukan perubahan radikal. Tujuannya: mengembalikan secepatnya PKI sebagai pelopor kelas buruh.
Seakan untuk memamerkan pengaruhnya, pada 22 Agustus 1948 di Yogyakarta, Musso menggelar rapat raksasa. Dalam rapat yang dihadiri sekitar 50 ribu orang itu, dia meneriakkan pentingnya mengganti kabinet presidensial menjadi kabinet front nasional. Musso juga menyerukan perlunya menggalang kerja sama internasional untuk meratifikasi hubungan diplomatik secepat mungkin, terutama dengan Uni Soviet. Hubungan dengan negara itu, menurut dia, bisa mematahkan blokade Belanda.
Untuk menyebarkan gagasan revolusi Jalan Barunya, bersama pimpinan PKI, pada September 1948, Musso melakukan safari ke sejumlah daerah, antara lain Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo.
Di tengah safarinya itulah, pada 18 September, meletus peristiwa Madiun yang kemudian dikenal sebagai Madiun Affair. Dipimpin Soemarsono, pasukan Brigade 29, yang didominasi Pesindo, melakukan aksi sepihak. Mereka melucuti pasukan Brimob dan menyerang pasukan Divisi Siliwangi. Setelah menguasai Madiun, mereka mendeklarasikan pemerintahan Front Nasional sesuai dengan anjuran “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” Musso.
Sebulan Bersama Oude Heer
Rapat Politbiro Partai Komunis Indonesia, Agustus 1948, adalah panggung pertama bagi Musso setelah 21 tahun menghilang dari Republik. Pada 1927 ia kabur ke Moskow akibat terlibat pemberontakan PKI 1926 yang dapat dipadamkan Belanda. Pada 1935 ia pernah menyusup ke Surabaya untuk menghidupkan kembali PKI. Tapi ia tak berhasil.
Sejak itu PKI menjadi partai bawah tanah yang melawan fasisme secara lunak. PKI tak menggalang massa buruh dan tani, tapi menyusup ke pemerintah dan organisasi lain. Musso menilai cara itu tak efektif.
Dalam gagasan barunya, “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”, Musso menganggap PKI tidak mengakar kuat pada buruh, tani, pemuda, dan tentara. Kader PKI terpecah akibat disusupkan ke pemerintah atau partai lain. Sosialisasi ideologi partai lembek karena tidak dilakukan secara terbuka. Sebagai partai bawah tanah PKI ketika itu lebih banyak berlindung di balik Front Demokrasi Rakyat (FDR).
Didirikan di Solo pada 26 Februari 1948 sebagai akibat jatuhnya kabinet Amir Sjarifoeddin, FDR menampung partai dan ormas sayap kiri. Selain PKI ilegal, anggota front itu adalah Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Tani Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Indonesia. Amir sendiri didapuk menjadi Ketua Front.
Menurut sejarawan Belanda, Harry A. Poeze, FDR dibentuk setelah Amir dan Sutan Sjahrir pecah kongsi dalam Partai Sosialis. Amir menghendaki partai memihak Soviet dan menentang kapitalisme pimpinan Amerika Serikat. Sjahrir berpendirian partai harus menempuh politik luar negeri bebas aktif.
Jatuhnya kabinet Amir memperparah perseteruan itu. Sjahrir akhirnya keluar dari Partai Sosialis dan membentuk Partai Sosialis Indonesia. Adapun Partai Sosialis Amir melebur ke FDR.
Dalam dokumen FDR, “Menginjak Tingkatan Perjuangan Militer Baru”, disebutkan bahwa aliansi itu dibentuk untuk menggulingkan kabinet Hatta yang tengah berkuasa. Penggulingan itu akan dilakukan melalui parlemen, bahkan jika perlu membentuk pemerintahan baru melalui pemberontakan.
Amir menyambut gagasan Musso. Dalam rapat Majelis Lengkap FDR, Agustus 1948, ia berujar, “Kedatangan Oude Heer (Pak Tua) Musso bisa mempercepat proses yang selama ini kita jalankan.” Dalam bukunya, Madiun dalam Republik ke Republik (2006), mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Himawan Soetanto menyatakan kembalinya Musso membawa haluan baru yang menekankan perlawanan terhadap fasisme secara radikal.
Musso tidak mau menyia-nyiakan waktu. Di panggung rapat Politbiro PKI, ia meminta partai itu bersalin rupa. Menurut mantan Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat DI Yogyakarta Hersri Setiawan, di mata Musso PKI ilegal melakukan beberapa kesalahan, di antaranya partai tidak berani melakukan perjuangan bersenjata dan lebih memilih politik kompromi. Partai juga dianggap tidak mengedepankan ideologi komunis. “Musso menuntut gerakan PKI direvisi,” kata Hersri.
Rapat itu akhirnya memutuskan hanya perlu satu partai kiri yang legal untuk menyatukan gerakan buruh dan kaum miskin. Pada rapat FDR, 21 Agustus 1948, Politbiro PKI mengusulkan agar ketiga partai di FDR melebur menjadi satu dan menyandang nama Partai Komunis Indonesia.
Dalam korespondensinya dengan ahli politik Ben Anderson, mantan Ketua Bidang Pertahanan Pesindo Soerjono menyatakan usulan itu ditolak pemimpin Partai Buruh, seperti Asrarudin dan S.K. Trimurti. Mereka meminta Front menggelar kongres sebelum melebur menjadi PKI.
Sejumlah kader partai di FDR memang meragukan kemampuan Musso, tokoh lama yang tiba-tiba ingin mengambil alih kepemimpinan partai kiri. Sejumlah kader Pesindo dan Barisan Tani Indonesia yang semula pro-Sjahrir memilih hengkang. “Kerikil ini menyebabkan PKI baru tidak solid,” kata sejarawan Rushdy Hussein.
Namun upaya penyatuan itu tak terhindarkan. Umumnya pemimpin partai kiri mempercayai Musso. Pada Kongres PKI, 27 Agustus 1948, penyatuan itu disahkan. Awal September dibentuklah kepengurusan PKI legal dengan Musso sebagai pemimpin. Kepengurusan itu menandai masuknya PKI ke kancah politik terbuka. Belum genap sebulan muncul ke permukaan, meletuslah pemberontakan Madiun yang dilakukan organ PKI pimpinan Musso. Setelah peristiwa itu, PKI kembali remuk redam.
Suatu Malam di Proklamasi 56
Lelaki yang mengenakan safari warna gelap itu berjalan sendirian. Suatu hari pada Januari 1948, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan raut wajah kusut dia mendekati beberapa pemuda yang tengah duduk santai di belakang rumah Presiden Sukarno di Jalan Proklamasi 56, Pegangsaan, Jakarta Pusat.
Rumah ini memang menjadi tempat bersantai para pejabat negara dan aktivis kemerdekaan di malam hari. Setelah menyapa sekadarnya, dia mengeluarkan sebotol kecil wiski dari kantong celana, kemudian menenggaknya. Lelaki itu adalah Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri Indonesia yang beberapa hari sebelumnya “dipaksa” meletakkan jabatan.
“Malam itu kami minum wiski bersama,” kata Rosihan Anwar mengenang peristiwa itu. Dalam penglihatan wartawan senior ini, Amir terlihat agak tertekan setelah lengser dari jabatan perdana menteri. “Meski dia berusaha menutupi dengan tetap terlihat enjoy,” katanya.
Amir terpaksa melepaskan jabatan perdana menteri setelah meneken Perjanjian Renville. Tekanan dari lawan politiknya kian menjadi-jadi. Sebagai kepala pemerintahan, dia dinilai bertanggung jawab atas semakin terpojoknya posisi Indonesia setelah perundingan itu.
Wajah Amir Sjarifoeddin tampak sumringah pagi itu, 8 Desember 1947. Di atas kapal USS Renville dia asyik berbicara tentang Frank Graham, perwakilan Amerika Serikat di Komisi Tiga Negara. “Mereka rileks sambil masing-masing memegang Injil di tangan,” kata Rosihan. Pemimpin redaksi koran Siasat itu mengaku melihat pertemuan tersebut saat mengunjungi kapal perang milik Amerika yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Perundingan Renville terjadi atas desakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Agustus 1947, yang khawatir melihat pertikaian Indonesia-Belanda yang berlarut-larut. Dalam resolusinya itu, Dewan Keamanan mendesak kedua negara agar menyelesaikan pertikaian dengan menunjuk tiga negara sebagai penengah.
Indonesia memilih Australia, Belanda menunjuk Belgia. Dua negara itu kemudian menunjuk Amerika sebagai anggota ketiga. Persekutuan ini kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara, yang diwakili Frank Graham (Amerika), Richard Kirby (Australia), dan Paul van Zeeland (Belgia).
Sebelum berunding, di dalam negeri, Amir pasang kuda-kuda. Dia merangkul kembali Masyumi agar mau bergabung di pemerintahan. Tawaran itu diterima tanpa syarat. Pada 11 November 1947, Amir merombak kabinet dengan memberikan lima kursi menteri untuk Masyumi.
Namun harapan tinggal harapan. Baru saja perundingan dibuka, delegasi Belanda menolak usul Indonesia untuk menyelesaikan persoalan politik sebelum membicarakan soal gencatan senjata.
Tak hanya itu, Belanda juga menolak tuntutan komisi teknis Indonesia yang diketuai J. Leimena agar tentara kompeni ditarik kembali hingga batas garis demarkasi yang telah disepakati bersama 14 Oktober 1946. Sebaliknya, Belanda menuntut batas demarkasi itu adalah kesepakatan baru pada 28 Agustus 1947, yang disebut sebagai Garis van Mook. Pembahasan di komisi teknis buntu.
Macetnya pembahasan di komisi teknis membuat Amir jengkel dan mengancam akan kembali ke Yogyakarta. “Kapan saya kembali ke Jakarta tergantung Belanda. Saya hanya kembali jika ada sesuatu yang harus dikerjakan,” katanya seperti dikutip Naskah Lengkap Asal-Usul KTN. Karena tak diindahkan, pada 24 Desember 1947, Amir kembali ke Yogyakarta.
Pada saat yang sama, di sejumlah daerah tentara Belanda terus melakukan aksi militer. Tersiar kabar akan ada aksi militer besar-besaran ke Yogyakarta, jika Indonesia tetap ngotot menolak 12 prinsip politik Belanda. Kondisi semakin genting. Frank Graham sebagai utusan Komisi Tiga Negara menggelar pertemuan dengan “Lima Besar RI”, yaitu Sukarno, Moh. Hatta, Soetan Sjahrir, Amir, dan Agus Salim. Graham meminta Indonesia tidak meninggalkan meja perundingan. Tidak memiliki pilihan, Indonesia akhirnya mengalah dan menerima tuntutan Belanda. Kemudian, 17 Januari 1948, di atas kapal Renville, Amir meneken persetujuan itu.
Para pemimpin Republik mendukung. Presiden Sukarno mengatakan, meski Perjanjian Renville seakan-akan merugikan Indonesia, harus dilihat kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh. “Kalau bisa mencapai cita-cita dengan jalan damai, kenapa harus perang,” katanya. Hatta mengatakan perjanjian ini tidak menjauhkan kita dari cita-cita. Panglima Besar Sudirman juga mengaku puas atas pencapaian itu.
Di luar dugaan Amir, partai-partai pendukungnya justru menolak Perjanjian Renville. Sehari setelah perjanjian itu, sekitar 300 orang yang mengaku sebagai massa Hisbullah menggelar demonstrasi di depan Istana Yogyakarta. “Kabinet Amir Bubar. Kami menolak Perjanjian Renville,” demikian kata salah satu dari mereka. Sumpah-serapah juga diarahkan ke Perdana Menteri, “Amir pengkhianat.”
Pemimpin Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia juga menyalahkan Amir. Mereka mengatakan menarik dukungan dari pemerintahan dan mengumumkan pengunduran diri para menteri. Presiden Sukarno yang semula mendukung kini berbalik. “Sebaiknya serahkan mandat kepada saya,” kata Sukarno.
Amir tidak bisa berbuat banyak. Pada 23 Januari 1948, dia menyatakan mundur. Sukarno kemudian menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Hatta yang kemudian membentuk kabinet baru. Masyumi dan PNI, dua partai yang sebelumnya meninggalkan Amir, kemudian memutuskan bergabung di kabinet Hatta.
Menurut Soemarsono, anggota Pimpinan Pusat Pesindo, Amir saat itu merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan politik. “Aduh, begini permainan komplotan ini,” katanya mengutip keluhan Amir.
Kepedihan Amir tak berujung di situ. Di kalangan kelompok kiri, dia juga disalahkan, dinilai terlalu lemah dan mau begitu saja menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri. Menurut Soemarsono, sebuah rapat mendadak digelar kelompok kiri untuk mengadili Amir. “Semua yang hadir menyalahkan dia karena mau mundur begitu saja,” katanya.
Pemimpin Partai Komunis Indonesia, Musso, dalam dokumennya, Jalan Baru untuk Republik Indonesia, juga menyerang ketidakberdayaan Amir. Menurut dia, kaum komunis saat itu melupakan ajaran Lenin yang menyatakan pokok dari revolusi adalah kekuasaan negara. “Mundurnya Amir memberi jalan elemen borjuis memegang kendali pemerintah,” katanya.
Semua ini berlangsung cepat: Amir mendapati dirinya sekonyong-konyong jadi musuh bersama. Tak mengherankan malam itu di belakang rumah Sukarno dihabiskan sampai larut dengan minum wiski dan bernyanyi. Menurut Rosihan, pertemuan malam itu adalah terakhir kali dia bersua dengan Amir. “Setelah itu, saya hanya mendengar dia pergi ke Solo membentuk Front Demokrasi Rakyat,” katanya. “Sampai akhirnya ditembak mati.”
Mitos Amerika di Kaki Lawu
Di ketinggian seribu dua ratus meter, telaga itu membentang. Airnya tenang, dengan kedalaman hampir tiga puluh meter. Hawa sejuk senantiasa merapat di sekitarnya. Gunung Lawu yang menjulang kukuh terlihat menancapkan kakinya. Keindahan panoramanya membuat wisatawan rajin berlabuh di Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti memenuhi hasrat turis, banyak hotel dan vila mengitari telaga seluas tiga puluh hektare ini.
Dulu pun orang-orang Belanda membangun rumah dan hotel di kawasan Sarangan. Tapi, pada saat Agresi Militer Belanda Kedua, akhir 1948, tentara Republik membakar bangunan-bangunan itu. Sebagian sisa bangunannya masih terlihat hingga kini.
Di sini pula, tersimpan rumor tentang pertemuan pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia. Satu pertemuan yang oleh pihak komunis diduga ikut mempengaruhi penyingkiran orang-orang kiri oleh Kabinet Hatta dalam Peristiwa Madiun pada September 1948.
Tuduhan keterlibatan Amerika di Madiun pada 1948 muncul setelah peristiwa itu sendiri. Adalah Paul de Groot, pemimpin komunis di Belanda, seperti ditulis ahli Asia Tenggara dari Universitas Cornell, Ann Swift, dalam disertasinya berjudul The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948, yang membuka teori provokasi Peristiwa Madiun oleh Amerika.
Di hadapan parlemen Belanda, sebulan setelah Peristiwa Madiun, De Groot menuduh Charlton Ogburn, penasihat politik delegasi Amerika dalam Komite Jasa Baik untuk Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertemu dengan Sukarno dan Hatta di Sarangan, tiga bulan sebelum Peristiwa Madiun meletus. Dalam pertemuan ini, Amerika menjanjikan pengiriman senjata dan penasihat teknis jika pemerintah Indonesia mau menyingkirkan komunis. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Menteri Penerangan Mohammad Natsir.
Belakangan, tuduhan De Groot ini diadopsi oleh komunis Rusia pada Januari 1949. Tiga tahun setelah Peristiwa Madiun, wartawan Prancis, Roger Vailland, juga menuliskan pertemuan itu dalam Boroboudour, Voyage Bali, Java et autres Iles. Versi Roger ini ditelan oleh majalah Bintang Merah milik PKI.
Berdasarkan tulisan Roger, pertemuan Sarangan digelar pada 21 Juli. Indonesia diwakili Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta, Menteri Penerangan Mohammad Natsir, Menteri Dalam Negeri Soekiman Wirjosandjojo, Mohamad Roem, dan Kepala Kepolisian Soekanto. Dari pihak Amerika, hadir Duta Besar Merle Cochran dan penasihat Presiden Harry Truman, Gerard Hopkins.
Pertemuan ini disebut menghasilkan Red Drive Proposal. Salah satu isinya, Amerika memberikan US$ 56 juta untuk menghancurkan PKI. Bintang Merah juga menyebutkan Kabinet Hatta menggunakan Rp 3 juta untuk menyogok Dokter Muwardi, pemimpin Gerakan Revolusi Rakyat, untuk membuat insiden Solo yang kemudian memunculkan Peristiwa Madiun.
Mantan Gubernur Militer Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun Soemarsono meyakini adanya Red Drive Proposal. Soemarsono mengaku mendengar dari mantan perdana menteri Amir Sjarifoeddin-yang digantikan Hatta setelah Perundingan Renville-soal pertemuan itu. Amir mengatakan adiknya saat pertemuan itu menyaksikan siapa saja yang hadir. Sukarno saat itu hanya diam. Sedangkan Hatta menyetujui tawaran Amerika. “Yang banyak bicara Hatta, Soekiman, dan Roem,” katanya.
Menurut Soemarsono, seperti tertulis dalam buku Revolusi Agustus, saat itu PKI memang menghadapi gerakan antikomunis dari sejumlah pihak. Partai Nasional Indonesia dan Masyumi, misalnya, semula mendukung Amir Sjarifoeddin yang memimpin delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville. Tak lama setelah perundingan itu, PNI dan Masyumi berbalik menentang hasil Perundingan Renville-yang akhirnya menjatuhkan Amir dari jabatannya. Belakangan, kabinet Hatta yang melaksanakan Perundingan Renville justru menyertakan orang-orang PNI dan Masyumi.
Inilah yang membuat PKI yakin, penyingkiran orang-orang kiri sudah direncanakan setelah Perundingan Renville. Soemarsono tak heran, Hatta yang sering berseberangan dengan PKI, dan Menteri Dalam Negeri Soekiman yang tokoh Masyumi, menyetujui pemberangusan kaum kiri pada saat pertemuan Sarangan. Kondisi ini sejalan dengan niat Amerika membendung komunis di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, Sukarno menginginkan pengakuan kedaulatan dari negara Barat. “Bung Karno waktu itu berpihak pada Hatta,” kata Soemarsono.
Banyak pihak meragukan adanya pertemuan Sarangan. Hersri Setiawan, mantan tahanan politik di Pulau Buru yang pernah mewawancarai Soemarsono, mengatakan pernah mencoba menelusuri dokumen pertemuan itu. Tapi nyatanya tak ada satu pun dokumen kuat yang mampu menjelaskan pertemuan dan Red Drive Proposal. “Saya menyimpulkan (proposal) itu mengada-ada,” katanya.
Sejarawan Rushdy Hussein menilai gejala keterlibatan Amerika memang ada. Misalnya, setelah Perundingan Renville, Amerika yang tadinya mendukung Belanda berbalik arah ke Indonesia. Selain itu, pihak komunis menganggap Kepala Kepolisian Soekanto merupakan binaan Amerika karena pada 1948 menjalani pelatihan di sana. “Tapi semua itu hanya gejala psikologis. Kaitannya tidak langsung. Pertemuan Sarangan bisa dianggap sebagai mitos,” ujar Rushdy.
Ann Swift malah menunjukkan kelemahan mendasar versi PKI yang menganggap pertemuan dilakukan pada 21 Juli 1948. Padahal, “Merle Cochran baru tiba di Indonesia pada 9 Agustus 1948,” tulis Swift.
Toh, Swift menunjukkan Cochran membujuk Sukarno dan Hatta agar mengeliminasi komunis dari Indonesia, seperti tertulis dalam dokumen milik kantor Hubungan Luar Negeri Departemen Pertahanan Amerika. Dokumen itu menyebutkan, Cochran rajin menemui Presiden dan Perdana Menteri. Ia khawatir, komunis akan menjatuhkan kabinet Hatta. Sebagai imbalan menumpas komunis, Amerika akan mengupayakan kesepakatan dengan Belanda yang lebih bisa diterima, meski sebelumnya Amerika lebih berpihak kepada Belanda untuk melawan blok Soviet di Eropa melalui bantuan Marshall Plan. Indonesia pun memanfaatkan ketakutan Amerika sebagai tekanan mengupayakan kesepakatan dengan Belanda.
Swift menilai peran Cochran yang memang antikomunis sangat besar dalam membujuk pelenyapan kaum Marxis. Meski menyarankan Hatta segera mengambil tindakan militer kepada komunis, Cochran tak terlihat menawarkan bantuan senjata.
Menurut Swift, pada 6 September, seorang pejabat tinggi Indonesia, diduga dari Masyumi, mengirim telegram ke Konsul Jenderal Amerika di Jakarta. Isinya, Hatta telah menyiapkan aksi tanpa kompromi terhadap komunis. Tapi Hatta membutuhkan bantuan untuk mengatasi kesulitan yang mungkin muncul.
Belanda sempat menawarkan bantuan tapi ditolak. Saat itu Amerika hanya menjawab upaya terbaik dari Hatta akan menjadi pintu kesepakatan dengan Belanda. Jika kesepakatan itu terjadi, Amerika akan membantu perekonomian Indonesia. Belakangan, saat berbicara dengan Cochran setelah Peristiwa Madiun, Hatta sendiri mengatakan membutuhkan peralatan persenjataan kepolisian. Tapi Cochran menjawab bantuan ekonomi tersedia begitu federasi Indonesia tercipta.
Entah ada entah tiada bantuan dari Amerika, yang jelas, penumpasan PKI di Madiun akhirnya terlaksana. Pada 1 Oktober 1948, Konsulat Amerika menyatakan Peristiwa Madiun sebagai “kekalahan pertama komunis”.
Di Hotel Huisje Hansje, Red Drive Proposal disebut-sebut ditawarkan Amerika kepada pemerintah Indonesia. Tapi pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia serta warga setempat tak tahu persis lokasi hotel itu. Bung Karno memang pernah ke Sarangan sebelum Peristiwa Madiun. Saat itu ia membawa istrinya, Fatmawati, dan kedua anaknya, Megawati Soekarnoputri dan Guntur Soekarnoputra. “Tapi menginapnya di Hotel Merdeka,” kata bekas karyawan Hotel Merdeka, Sukarno.
Sejarawan Rushdy Hussein pernah mencari Hotel Huisje Hansje. Tapi tak ada petunjuk apa pun yang ditemukannya. Rushdy menduga, hotel itu ikut dibakar pada saat Agresi Militer Belanda Kedua. Huisje Hansje seperti lenyap membawa mitos bernama Red Drive Proposal.
Laga Pengalih Sebelum Madiun
Bakda isya, Kolonel Sutarto sampai di depan rumah ibunya di Kampung Timuran Solo. Malam itu, 2 Juli 1948, komandan Pasukan Panembahan Senopati (KPPS) ini bergegas pulang begitu menerima kabar ibunya sakit keras.
Begitu paniknya, Sutarto jadi tak awas terhadap sekitarnya. Turun dari jip yang membawanya dari markas, bekas Shodancho Daidan Peta di Wonogiri itu disambut tembakan dari kegelapan. Dor… dor…. Sutarto ambruk. Dua peluru menembus belakang tubuhnya. Ia tewas bersimbah darah.
Insiden itu memicu beragam kecurigaan. Selain pelakunya tak tertangkap, korbannya adalah panglima sebuah kesatuan tempur paling besar dan berpengaruh di wilayah Surakarta.
Belakangan muncullah desas-desus. Di lingkungan prajurit Senopati beredar kabar, Sutarto ditembak anggota pasukan Siliwangi, anak buah Letnan Kolonel Sadikin. “Karenanya, anggota pasukan Senopati diperintah mencari tahu,” kata Mayor Slamet Rijadi dalam buku biografinya, Dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS.
Muncul spekulasi baru. Sutarto sengaja ditembak karena dianggap melawan Program Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara yang digulirkan kabinet Hatta. Sutarto menganggap program ini tak transparan dan mengancam posisi pasukannya.
Front Demokrasi Rakyat/PKI yakin pembunuhan Sutarto adalah teror politik gaya Hatta. “Ini rasionalisasi dalam bentuk lain. Kami yakin Hatta sendiri yang langsung turun tangan karena dia Menteri Pertahanan saat itu,” kata Soemarsono, mantan Gubernur Militer Pemerintahan Front Nasional Daerah Madiun.
Spekulasi ini menguat karena insiden penembakan Sutarto terjadi selang 40 hari setelah ia memimpin parade pasukan di Solo, 20 Mei 1948. Di depan Presiden Sukarno dan Panglima Besar Sudirman, Sutarto menggelar lima resimen tempurnya, termasuk enam resimen laskar rakyat, seperti pasukan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan Tentara Laut Republik Indonesia, yang dikenal kiri.
Belakangan, Divisi IV Panembahan Senopati batal dilikuidasi. Menanggapi aksi penolakan itu, Panglima Sudirman menjadikan pasukan Sutarto sebagai pasukan komando khusus.
Program kabinet Hatta so-al Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) Tentara yang ditentang Sutarto menyorongkan konsep penataan postur angkatan perang yang lebih ramping dan efisien. Hatta beralasan, kocek negara yang mepet dan wilayah Indonesia yang kian menciut akibat Perjanjian Renville menjadi pertimbangan Re-Ra. Hatta, seperti dikutip dalam otobiografinya, merujuk setidaknya ada 350 ribu tentara plus 400 ribu anggota laskar yang kudu diciutkan menjadi 160 ribu hingga 57 ribu prajurit reguler.
Perampingan itu dimulai dengan penataan struktur garis dan wilayah komando. Besaran divisi dan kesatuan komando teritori juga diciutkan. Jawa, misalnya, dari tujuh divisi menjadi empat divisi. “Semuanya disesuaikan dengan fungsi pertahanan menghadapi agresi Belanda,” kata Nasution dalam Tentara Nasional Indonesia.
Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Madiun, dari Republik ke Republik, Program Re-Ra justru bermasalah saat diberlakukan di lapangan. Misalnya friksi akibat audit personel sesuai dengan kepangkatan dan tingkat pendidikan antara perwira eks Peta dan eks KNIL. Eks Peta, misalnya, turun sampai dua tingkat (dari letnan satu menjadi pembantu letnan satu). Adapun perwira eks KNIL naik pangkat dua tingkat.
Menurut Soemarsono, sejatinya FDR/PKI adalah kelompok yang paling dirugikan dengan Re-Ra. Barisan laskar yang dibangun FDR, seperti Pesindo, biro perjuangan, perwira politik, dan TNI Masyarakat, akan dilikuidasi karena dianggap bukan TNI. “Sebenarnya kamilah sasaran tembak utama kabinet Hatta,” kata Soemarsono dalam bukunya, Revolusi Agustus.
Soemarsono sendiri dipecat dari Pendidikan Politik Tentara pada awal Mei 1948. Pangkat terakhirnya mayor jenderal. Pada bulan yang sama, dipecat pula Wikana, eks Gubernur Militer Surakarta. Wikana adalah tokoh FDR dan Pesindo. Menyusul kemudian pembubaran TNI Masyarakat yang dirintis Joko Suyono dan Sakirman.
Menurut Himawan, FDR berang karena penataan sistem komando TNI bisa menghancurkan upaya FDR membangun kekuatan sejak 1945. Setidaknya 35 persen dari TNI pada masa itu sudah dipengaruhi “kelompok kiri”. Beberapa di antaranya bahkan panglima kesatuan tempur. “Wajar kalau penolakan para perwira terhadap Re-Ra kemudian dimanfaatkan tokoh-tokoh kiri,” kata Himawan.
Himawan merujuk sikap keras Divisi VI Narotama, Jawa Timur, dan Divisi IV Panembahan Senopati. Sutarto sendiri dicap “kiri ” karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh Front Demokrasi Rakyat/PKI. Menurut Himawan, sebenarnya ada faktor lain yang mendorong penolakan perwira daerah terhadap Re-Ra, yakni sentimen atas perlakuan istimewa Hatta terhadap kesatuan Siliwangi-setelah pasukan Siliwangi terpaksa hijrah ke Surakarta, pasca-Renville, dan Hatta kemudian mempromosikan eks Panglima Siliwangi Kolonel A.H. Nasution sebagai wakil Panglima Sudirman. Sosok Nasution dianggap menjadi ancaman terhadap wibawa Sudirman sebagai panutan mereka.
Sebagai kota terbesar kedua di Republik setelah Yogyakarta, Solo pada 1948 sudah padat dengan aneka pendatang dan pengungsi, antara lain Brigade II Siliwangi pimpinan Sadikin. Buat pasukan setempat, kehadiran Siliwangi dianggap sebagai “intruders” atau orang-orang asing yang mengganggu rumah tangga mereka.
Kontak senjata terbuka antara KPPS dan Siliwangi bisa dicegah berkat langkah bijak Komandan Komando Militer Kota Solo Mayor Achmadi. Belakangan terbukti Sutarto dibunuh Pirono atas suruhan tokoh PKI, Alimin.
Ketegangan makin memuncak ketika perwira ALRI-Gajah Mada yang juga tokoh FDR, Mayor Esmara Sugeng, dan enam perwira KPPS lainnya “dibawa” ke Siliwangi. Para perwira itu dikabarkan ditawan di asrama kompi Siliwangi yang dipimpin Kapten Oking di Srambatan, tak jauh dari Stasiun Balapan.
Puncaknya pada 13 September 1948. Markas Siliwangi diserbu pasukan Senopati. Pertempuran berlangsung sengit dan jatuh korban. Letkol Soedi, Panglima KPPS, melaporkan insiden penculikan para perwiranya ke Panglima Sudirman. Ia juga mengultimatum agar perwira yang diculik dibebaskan sebelum pukul 12.00 WIB.
Ketegangan itu membuat Sudirman turun tangan. Namun sejumlah perundingan yang digelar tak banyak menyelesaikan masalah. Letnan Kolonel Sadikin tetap emoh melepas para perwira KPPS dengan alasan tidak tahu ada penculikan-meski belakangan akhirnya enam perwira itu diketahui ditahan di penjara Wirogunan, Yogya.
Gencatan senjata yang digariskan Sudirman dalam perundingan di Balai Kota Solo toh tak ditaati. Esok harinya, 16 September, giliran Markas Pesindo di Jalan Singosaren diserbu. Selain pasukan Siliwangi, ikut juga Barisan Banteng dan GRR. Ketegangan menjalar ke seluruh penjuru Solo.
Sudirman akhirnya mengeluarkan keputusan harian yang intinya peristiwa di Surakarta menyinggung kedaulatan Angkatan Perang. Karena itu, komandan kesatuan diminta bertanggung jawab. Sudirman juga menyampaikan, pucuk pimpinan negara telah sepakat akan melakukan tindakan tegas di daerah mana pun yang terancam bahaya.
Presiden Sukarno menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer. Keputusan itu, menurut Nasution, diambil bersama Sudirman. Mereka bertiga akhirnya bertemu dengan Sukarno di Gedung Agung Yogyakarta sekitar pukul 23.00 WIB.
Di Solo, 18 September 1948, Gubernur Militer Solo Gatot Subroto meminta aksi tembak dihentikan. Gatot juga menyatakan batalion Ahmad Jadau, Soejoto, dan Dahlan dinyatakan liar.
Clash antarkesatuan di Solo ternyata dipantau penuh oleh Belanda. Pusat Dinas Intelijen Militer Belanda, Centrale Militaire Inlichtingen Dienst, pada 23 September 1948, seperti dikutip Himawan, menyebut Solo memang akan dijadikan “Wild West” oleh kelompok Musso sebagai pengalih perhatian dari gerakan yang terjadi di Madiun.
Disebutkan pula, sesungguhnya pertikaian bersenjata itu adalah antara dua pasukan yang sama-sama berhaluan komunis, yaitu Divisi IV Panembahan Senopati-di bawah pengaruh Alimin, Musso, dan Amir Sjarifoeddin-dan Satuan Divisi Siliwangi di bawah pengaruh pemimpin komunis seperti Tan Malaka dan Dr Muwardi.
Infiltrasi ke Siliwangi, kata dokumen itu, dilakukan sejak 1947 oleh satuan eks Brigade Tjitarum, pasukan Tan Malaka. “Mereka sama-sama mau merebut kekuasaan komunis, tapi beda kiblat,” kata sejarawan Rushdy Hussein.
Karena itu, menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, pertempuran ala “koboi” di Solo seperti lingkaran. “Hanya berputar-putar antara Musso dan Tan Malaka. Dua-duanya siap meledak.”
Setelah Pistol Menyalak Tiga Kali
Kendati sudah bertahun-tahun tinggal di Belanda, Nugroho, 85 tahun, masih mengingat rumah besar yang berada paling dekat dengan jalan raya di kompleks Pabrik Gula Rejoagung di Madiun, Jawa Timur. Ia bercerita, 62 tahun lalu kompleks pabrik itu menjadi markas Badan Kongres Pemuda.
Nugroho bekerja di bagian penerangan badan itu. Ia ingat saat itu Rejoagung di bawah kendali Soemarsono yang ditugasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) menjadi Ketua Badan Kongres Pemuda Madiun.
Rumah itu pula yang pada pekan ketiga September 1948 berkali-kali didatangi orang berseragam militer. Tamu yang datang itu adalah orang-orang bekas Laskar Pemuda Sosialis yang masuk jadi tentara di Brigade 29.
Soemarsono memang sudah tak lagi bertugas di militer sejak dipecat Perdana Menteri Mohammad Hatta dari Pendidikan Politik Tentara. Oleh Hatta bintang dua di pundaknya juga dilucuti. Tapi ia masih punya pengaruh karena merupakan salah satu pentolan Pesindo.
Saban kali bekas anak buahnya datang, yang dibawa adalah kabar-kabar buruk. “Mereka melaporkan ada pasukan dengan badge tengkorak berlatih menembak dekat markas mereka,” kata Soemarsono.
Lain waktu mereka melaporkan hilangnya tiga pemimpin pemogokan Serikat Buruh Daerah Autonom. Penculiknya ditengarai pasukan tengkorak tadi. Kelompok bersenjata yang sama juga dituding menembak anggota Serikat Buruh Kereta Api.
Nugroho, tukang gambar poster Badan Kongres Pemuda, bercerita saat itu situasi Madiun memang panas. “Ada tentara, ada laskar macam-macam, dan mereka sering bentrok,” ujarnya. Yang paling mencolok, kata dia, adalah kelompok bersenjata dengan logo tengkorak di seragamnya.
Rentetan masalah itu mengingatkan Soemarsono akan cerita tiga perwira-Letnan Kolonel Suwardi, Komandan Angkatan Laut Solo Letnan Kolonel Achmad Jadau, dan Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang datang dari Solo, Jawa Tengah. Ketiga perwira ini menceritakan soal penembakan dan penangkapan orang-orang kiri di daerah mereka.
Soemarsono yakin hanya dalam hitungan hari masalah di Solo bakal sampai ke Madiun. Apalagi intelijennya di Polisi Militer dan Brigade Mobil bercerita ada instruksi dari pemerintah Mohammad Hatta untuk menangkap dirinya. Bahkan Brigade 29 juga akan dilucuti oleh Brigade Mobil Polisi.
Ia makin yakin saat didatangi kawan lamanya, Kolonel Moestopo, yang menyampaikan kabar senada. Moestopo, yang saat itu sudah bergabung dengan p asukan Siliwangi, bahkan mengatakan ia diperintahkan untuk menangkap Soemarsono. “Tangkap saja. Tapi apa mungkin menangkap saya tanpa saya melawan!” Soemarsono balik menghardik.
Pada 16 September, Soemarsono menerima telepon dari Kediri. Di ujung sambungan terdengar suara Panglima Divisi Brawijaya Kolonel Sungkono. Bekas tetangga Soemarsono saat tinggal di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur, itu mengajak bicara tentang ulah pasukan Siliwangi.
“Sudah, Cak, serang saja mereka. Masak sampean dari Surabaya bisa dihantam-hantam begitu?” kata Soemarsono menirukan ucapan Sungkono. “Hadapi saja Siliwangi itu, kami sepenuhnya di belakang Madiun.”
Digosok Sungkono, Soemarsono semakin panas. Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Rebut Kembali Madiun, Brigade 29 memiliki kekuatan sekitar lima batalion. Mantan Panglima Daerah Militer Siliwangi ini menjelaskan, pasukan yang dipimpin Kolonel Dachlan tersebut sudah bersiaga di seputar Madiun, yakni di Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, sampai ke lereng-lereng Gunung Wilis di Kediri.
Di lain pihak, pada awal September kelompok-kelompok di sekitar Madiun yang berpotensi menjadi lawan Soemarsono sudah diberangus. Itu yang dialami Pesantren Takeran di Magetan yang enggan mendukung gerakan kiri di sana. Satu per satu pemimpin pondok dijemput dan tak pernah kembali.
Madiun sendiri jadi basis massa yang solid buat gerakan ini karena kota itu punya bengkel kereta api dan banyak pabrik gula. “Mereka dapat dukungan dari buruh pabrik dan serikat buruh kereta api,” kata mantan Tentara Republik Indonesia Pelajar di Madiun, Yusuf Musdi.
Merasa di atas angin, Soemarsono pada 16 September berangkat meminta restu kepada Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri. Ia bercerita tentang kondisi Madiun dan kekhawatiran adanya penculikan terhadap komandan tentara yang berpihak ke Front Demokrasi Rakyat-organisasi yang menghimpun kelompok kiri, termasuk PKI.
Kepada Soemarsono, Musso bertanya tentang perimbangan kekuatan. “Tidak usah khawatir, saya kenal pasukan saya,” jawab Soemarsono. Kalau begitu bertindak saja, lucuti pasukan itu,” kata Musso lagi. Amir menimpali, “Bertindak saja, sebelum mereka bertindak.” Pertemuan larut malam itu berakhir. Soemarsono pamit dan Musso merangkulnya. “Saya bertindak itu atas perintah Musso,” ujarnya belakangan.
Namun peneliti sejarah dari Universitas Cornell, Ann Swift, meragukan klaim tersebut. Menurut dia, petinggi Front Demokrasi baru tahu setelah pelucutan selesai. Swift merujuk pada berita Madjallah Merdeka terbitan 30 September 1948, yang menyebut para aktivis Front yang kemudian tertangkap mengaku tak tahu-menahu rencana Soemarsono yang disebut “agak terburu-buru” itu.
Himawan Soetanto sependapat dengan Swift. Himawan melihat petinggi Front belum menghendaki gerakan bersenjata. Buktinya, kata dia, saat Peristiwa Madiun pecah, Musso dan Amir justru sedang bersafari di kota-kota lain buat menggalang dukungan.
Himawan yang ikut operasi Siliwangi menyerang Madiun juga menilai perhitungan Soemarsono meleset. Pasukan-pasukan yang dianggap bakal memberikan dukungan malah berbalik menggempur Soemarsono, termasuk Kolonel Sungkono.
Pada 17 September malam, suasana Pabrik Gula Rejoagung mencekam. Nugroho yang tinggal di Asrama Rejoagung diberi tahu malam itu akan terjadi sesuatu. “Kami diminta tenang dan jangan keluar,” katanya.
Lewat tengah malam terdengar letusan pistol. Tar, tar, tar! Tiga kali tembakan di pagi buta itu menandai bergeraknya serdadu Brigade 29.
Soemarsono, yang mengendalikan pasukan dari Rejoagung, mengirim pasukan merangsek ke tiga titik di Madiun: markas Polisi Tentara Republik Indonesia, markas Brigade Mobil Polisi, dan basis “pasukan tengkorak” di Maospati, daerah perbatasan dengan Magetan. “Saya putuskan menyerang duluan,” kata Soemarsono. “Bisa repot kalau saya harus menghadapi tiga pasukan itu sekaligus.”
Kalah dalam jumlah, lawan di markas Polisi Militer dan “pasukan tengkorak” dengan cepat ditekuk pasukan Soemarsono. Namun di markas polisi yang tak jauh dari Rejoagung terjadi perlawanan sengit. Menurut Nugroho, kontak senjata di markas polisi itu terdengar sampai asramanya di Rejoagung. “Suara tembakan baru berhenti sekitar pukul empat pagi,” ujarnya.
Nugroho bercerita, semua aktivis Badan Kongres baru berani keluar asrama saat hari sudah terang dan melihat barisan panjang polisi digiring pasukan Soemarsono. “Panjang sekali, saya lihat ada yang belum berpakaian,” ucapnya. “Semua digiring entah ke mana.”
Penyerangan rupanya meluas sampai ke tapal batas kota. Kantor polisi Gorang Gareng di perbatasan Madiun dan Magetan juga jadi sasaran. Sempat melawan, polisi akhirnya menyerah karena kehabisan peluru.
Enam jam setelah pistol menyalak di Rejoagung, Brigade 29 sukses memukul lawan-lawannya. Madiun dan sekitarnya dikuasai penuh pasukan Front Demokrasi Rakyat.
Menurut Soemarsono, cuma dua anak buahnya yang tewas. Saat pemakaman mereka, Soemarsono berseru lantang, “Van Madiun begint de victorie!” Dari Madiun kemenangan dimulai.
Kami Tidak Memberontak
Kini dia 89 tahun. Tapi ia bicara dengan tegas, jelas, sesekali meledak-ledak. Ingatannya terjaga baik, ia bercerita dengan runtut dan mendetail. Keriput di wajah, tubuhnya yang terlihat ringkih, tak kuasa menghalanginya bicara panjang lebar tentang sejarah pergerakan Indonesia. Ia menilai telah terjadi pemutarbalikan sejarah, dan itu tak adil baginya.
Soemarsono, mantan Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, juga bekas pemimpin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), menganggap Peristiwa Madiun adalah bagian penting dari sejarah hidupnya.
Dia berperan penting mengkoordinasi gerak cepat empat batalion Brigade 29, pasukan ABRI yang pro-Partai Komunis Indonesia, pada dinihari 18 September 1948. Dalam beberapa jam, Soemarsono dan pasukannya melucuti pasukan Siliwangi, Brimob, dan polisi militer di barak-barak mereka sendiri.
Sebagian besar anggota Brigade 29 memang eks anggota Pesindo. Soemarsono bersama pasukan ini bertarung hidup-mati mempertahankan Surabaya dari serangan Inggris, pada 10 November 1945. “Meski bukan komandan di pasukan itu, pengaruh saya besar,” kata Marsono, begitu dia biasa disapa, sambil tertawa.
Ditemui dua kali pada September lalu di rumah putrinya di Jakarta, Soemarsono, yang kini bermukim di Sydney, Australia, menceritakan kembali apa yang terjadi di Madiun dan sekitarnya pada akhir 1948. Ia tetap keras menolak peristiwa itu disebut sebagai pemberontakan.
Banyak yang menyebut Peristiwa Madiun 1948 merupakan pemberontakan PKI.
Saya menolak istilah pemberontakan untuk menyebut peristiwa yang terjadi di Madiun itu. Kami tidak berinisiatif untuk terlibat dalam bentrokan. Kami hanya membela diri.
Semua berawal dari pemogokan serikat buruh dalam negeri di Madiun pada awal September 1948. Mereka menuntut kenaikan upah dan berunjuk rasa di depan di kantor wali kota. Setelah mogok sehari, tiga orang pemimpin serikat itu hilang, diculik tentara.
Reaksi Anda?
Saya tentu bertanya kepada komandan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Madiun, Letkol Sumantri. Dia mengaku tidak tahu siapa yang menculik. Lho kok bisa, padahal kami mendapat informasi dari anak-anak Brigade 29 bahwa ketiga aktivis buruh itu ditahan di markas Siliwangi. Saya berkesimpulan, para penculik adalah tentara gelap yang tidak melapor saat masuk Madiun. Kami putuskan bergerak untuk membebaskan pemimpin buruh yang diculik.
Apa yang kemudian terjadi?
Saya akan ditangkap. Dokter Moestopo, kawan seperjuangan saya dari Surabaya, datang menemui saya di Pabrik Gula Rejoagung. Dia kolonel pasukan Siliwangi. Begitu bertemu, dia memeluk saya dan menangis. Saya bertanya, ada apa. Dia mengaku mendapat perintah untuk menangkap saya. Tentu saya marah. Saya berkata padanya, tangkap saja, tapi apa mungkin menangkap saya tanpa ada perlawanan.
Lalu?
Setelah itu, datanglah Kepala Korps Polisi Militer Madiun, Kapten Sunardi, ke tempat saya. Dia juga memberikan informasi bahwa saya akan ditangkap. Saya bertanya: soal apa. “Bung dianggap melawan pemerintah,” kata Sunardi. Staf intelijen Pesindo menyampaikan kabar serupa. Sejak itu saya lebih berhati-hati.
Anda merasa diteror?
Suatu hari, seseorang menembak saya di pekarangan rumah. Tapi tembakannya meleset, dan peluru kena pohon. Sejak itu, saya bersiap-siap. Pasti ada yang menteror. Saya siapkan pistol di mobil, meskipun saya pergi ke mana saja tanpa sopir. Mobil saya waktu itu Chevrolet tahun 1942.
Suasana Madiun saat itu?
Banyak informasi akan ada teror atas orang-orang kiri. Semua resah. Apalagi di Solo sudah ada pertempuran. Kami mendengar kabar, pasukan Brimob dan polisi militer akan melucuti Brigade 29. Kami tidak bisa tinggal diam.
Mengapa Anda merasa terdesak? Bukankah Madiun ketika itu basis PKI?
Sebenarnya keresahan sudah dimulai saat kabinet Amir Sjarifoeddin jatuh. Kabinet Hatta membuat kebijakan baru, yaitu rasionalisasi tentara. Semua laskar, yang kebanyakan anggotanya PKI, akan dikeluarkan dari militer. Kami, yang tidak pernah bersekolah formal, tidak akan pernah menjadi perwira. Pendidikan tentara Divisi Senopati, misalnya, paling tinggi ongko loro (kelas dua SD). Kami semua akan diganti dengan tentara sekolahan. Siliwangi yang akan paling diuntungkan.
Anda menuding Hatta ikut melakukan provokasi sampai terjadi Peristiwa Madiun?
Hatta jelas melakukan provokasi. Dia yakin, jika masih ada orang PKI di aparatur pemerintah, Barat tidak akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia juga membebaskan Tan Malaka. Padahal semua orang tahu Tan Malaka musuh orang-orang PKI.
Jadi, Anda yakin akan adanya Red Drive Proposal?
Itu jelas. Proposal itu terkait dengan proses pengakuan de jure masyarakat internasional atas Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat meminta agar orang-orang kiri di pemerintahan disingkirkan dulu. Jika itu dilakukan, baru Indonesia akan mendapat pengakuan.
Bagaimana Peristiwa Madiun bermula?
Saya yang bertindak duluan, pada dinihari 18 September. Tepat pukul dua pagi, kami melucuti pasukan Brimob, polisi militer, dan Siliwangi. Waktu itu jatuh korban tewas lima orang. Tiga orang dari mereka dan dua orang Brigade 29.
Jadi tidak benar bahwa di Madiun ketika itu semua bendera Merah Putih diganti bendera merah palu-arit, dan ada ribuan muslim dimasukkan ke penjara. Setelah pelucutan pasukan, situasi Madiun biasa-biasa saja.
Anda tidak berencana mengganti pemerintahan Sukarno-Hatta?
Saya hanya mau melucuti lawan, supaya mereka tidak bisa menyerang kami lebih dulu. Kami hanya membela diri. Kami juga tidak punya rencana pemberontakan. Buktinya, pada pagi harinya kami kirim telegram ke Yogyakarta, melaporkan situasi di Madiun.
Siapa yang mengirim telegram?
Supardi, Wakil Wali Kota Madiun. Semula saya minta komandan teritorial, Letkol Sumantri, yang melapor. Dia tidak berani. Residen Madiun, Samadikun, tidak ada di tempat. Wali Kota Madiun juga tidak berani. Ya sudah, saya tunjuk Supardi. Saya bilang, kamu sebagai wakil wali kota lapor saja, minta instruksi dari pemerintah Hatta di Yogya, apa yang harus dilakukan.
Di mana Musso saat itu?
Ia sedang melakukan tur ke daerah-daerah. Sebelumnya, dia sempat mampir ke Madiun. Sebelum memutuskan bergerak, saya sudah menemui Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri, di sebuah penginapan. Jadi saya bertindak atas perintah Musso.
Kalau bukan pemberontakan, mengapa ada proklamasi pemerintahan Front Nasional?
Itu bukan proklamasi pemerintahan baru. Kami hanya bersiap-siap, karena ada informasi bahwa kami akan diserang. Saat itu semua wakil partai juga diajak berembuk bersama di Balai Kota Madiun. Namun, setelah Sukarno berpidato di radio menuduh kami berontak, situasinya berubah. Pak Musso marah sekali. Pidato balasannya itu tanpa teks.
(Rosihan Anwar dalam sebuah tulisan pernah menuliskan keadaan ini. “Malam tanggal 19 September 1948 Presiden Sukarno bicara di depan RRI Yogya dan meminta rakyat memilih antara Muso-PKI dengan Sukarno-Hatta. Dalam waktu dua jam Muso tampil di depan radio Madiun dan mengatakan ‘rakyat seharusnya menjawab kembali bahwa Sukarno-Hatta adalah budak-budak Jepang, dan Amerika dan kaum pengkhianat harus mati’.” Red.)
Apa yang Anda lakukan setelah Peristiwa Madiun?
Saya disalahkan oleh pemimpin PKI yang baru di bawah D.N. Aidit. Saya di-black out oleh partai. Semua peran saya dihapus. Saya diminta tidak disiarkan sebagai orang yang terlibat peristiwa Surabaya 10 November, misalnya. Saya diminta menyingkir karena partai mau membangun kembali basisnya. Saya lalu pergi ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan menjadi guru di sana. Tapi, begitu pecah peristiwa 1965, saya ditangkap lagi oleh Orde Baru.
Misteri Surat Untuk Soekarno – Hatta
“Saya, sebagai perwira muda, saat itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik,” kata Soeharto dalam otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Ketika itu, perseteruan antara Perdana Menteri Mohammad Hatta dan kubu Front Demokrasi Rakyat, koalisi kekuatan “sayap kiri” di Indonesia, semakin runcing sejak Agustus 1948. Sedangkan Letnan Kolonel Soeharto-menurut buku tersebut-membaca situasi, mengamati setiap kubu, dan menganalisisnya dengan cermat.
Aroma perang saudara sudah begitu pekat di udara setelah pasukan Brigade 29 yang pro dengan tulang punggung Partai Komunis Indonesia, melucuti senjata pasukan Siliwangi di Madiun, Jawa Timur, pada 19 September 1948. Presiden Sukarno dan Musso, Pemimpin Partai Komunis Indonesia saling menyerang melalui pidato maupun tulisan mereka. “Bagimu adalah pilihan antara dua: ikut Muso dengan P.K.I.-nja jang akan membawa bangkrutnja tjita-tjita Indonesia Merdeka-atau ikut Sukarno-Hatta,” kata Sukarno dalam pidatonya hanya beberapa jam setelah pelucutan senjata.
Panglima Jenderal Sudirman tidak menginginkan anggota pasukan di Jawa Timur terseret konflik politik ini. Soeharto, yang dianggap netral, diutus membujuk Letnan Kolonel Soeadi, Komandan Pasukan Panembahan Senopati, supaya tidak bergabung dengan PKI. Soeharto dan Soeadi bertemu di Wonogiri, Jawa Tengah. Soeadi, yang memang condong ke PKI, malah mengajak Soeharto berkeliling meninjau kondisi Kota Madiun.
“Saya ditelepon Soeharto dari Mantingan (kecamatan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur),” ujar Soemarsono, Gubernur Militer Madiun ketika itu. Setelah tiba di Madiun, Soemarsono mengajak Soeharto berkeliling kota untuk menunjukkan tidak ada pemberontakan di kota itu. “Menurut pidato Sukarno, bendera Merah Putih di Madiun sudah diganti bendera palu arit. Saya minta Soeharto melihat mana ada bendera merah, semuanya bendera merah putih.”
Di rumah Residen Madiun yang ditinggali Soemarsono, Soeharto berjumpa dengan Musso yang sudah satu setengah bulan tiba di Indonesia. Selama berpuluh tahun, setelah pemberontakan PKI pada 1926 gagal, Musso tinggal di luar negeri. Baru kali itulah Soeharto bertemu Musso. Tokoh komunis itu mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan kopiah. Mereka kemudian berbincang-bincang. Soeharto menanyakan kepada Musso kenapa pemerintah dan Front Demokrasi royal malah ikut berseteru.
+ Apakah tidak sebaiknya kita tinggalkan permusuhan dan bersatu melawan Belanda?
– Bagi saya pun demikian, Bung Harto. Saya juga datang, kembali ke Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi rupanya Sukarno dan Hatta tidak senang kepada saya, mencurigai saya.
+ Kenapa tidak diadakan pembicaraan?
– Baru saja bertemu, tapi tidak ada kesepakatan.
+ Apakah boleh saya sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwa sebenarnya Pak Musso masih menginginkan persatuan?
– Ya, tolong sampaikan. Tapi terus terang, Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan.
Menurut penuturan Soemarsono, yang kini tinggal di Sydney, Australia, seusai pertemuan tersebut, dia meminta Soeharto membuat surat pernyataan bahwa situasi Madiun aman dan tak ada sinyal-sinyal pemberontakan. “Mas saja yang buat, saya tidak terbiasa,” kata Soemarsono mengutip jawaban Soeharto saat itu. Soemarsono meminta Soeharto menyampaikan surat itu ke Presiden Sukarno dan perdana menteri Hatta.
Mantan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin yang sudah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia juga menitipkan sepucuk surat untuk Presiden Sukarno. Amir, kata Soemarsono, mengirim surat pribadi yang berisi permintaan agar Bung Karno turun tangan mendamaikan kedua belah pihak.
Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan menyampaikan semua pernyataan Musso kepada Panglima Sudirman yang ketika itu sudah sakit keras. “Pak Dirman yang menyampaikan hasil pertemuan dengan Musso ke Bung Karno dan Bung Hatta,” kata Soeharto. Memang tak ada data sejarah menyatakan apakah pesan Musso itu sampai ke Sukarno dan Hatta. Yang pasti, perang saudara itu tak tercegah lagi. Dan Musso tewas di ujung senapan.
Sapu Bersih Pasca Madiun
Kabar itu tiba di Yogyakarta menjelang petang pada 18 September 1948. Isinya gawat: Partai Komunis Indonesia, dipimpin Musso, melancarkan aksi pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Menjelang magrib, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo dan Residen Surakarta Sudiro menemui Kepala Staf Operatif Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel Abdul Haris Nasution di rumahnya. “Presiden memanggil saya,” kata Nasution, seperti dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas.
Nasution kemudian menemui Presiden Sukarno di Gedung Agung-sebutan Istana Kepresidenan Yogyakarta, yang terletak di pusat kota. Presiden didampingi Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ketika itu Panglima Besar Jenderal Sudirman masih berada di Magelang. Menurut Nasution, Presiden memintanya membuat konsep tindakan yang akan diberlakukan sebagai keputusan presiden.
Kolonel Nasution kemudian menyodorkan rencana aksi militer kepada Sukarno. “Nasution menyatakan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan dan harus dilawan,” kata Harry A. Poeze, sejarawan asal Belanda, Rabu dua pekan lalu. Nasution sendiri dalam bukunya menyatakan, “Sebagai seorang yang telah berbulan-bulan langsung berhadapan dengan PKI, baik sebagai pejabat maupun pribadi, saya dapat konsepsikan dengan segera rencana pokok untuk menindak PKI.”
Isi rancangan keputusan presiden itu adalah perintah kepada Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menyelamatkan pemerintah dalam menindak pemberontakan, dan menangkap tokoh-tokohnya, serta membubarkan organisasi-organisasi pendukungnya atau simpatisannya. Nasution cemas, Front Demokrasi Rakyat, sayap oposisi kelompok kiri yang dipimpin Amir Sjarifoeddin dan Musso, melancarkan aksi serupa di Yogyakarta. Apalagi, satu hari sebelumnya, terjadi kontak senjata antara batalion Siliwangi dan pasukan Front Demokrasi di Solo.
Sukarno menyetujui rencana aksi Nasution. Presiden kemudian memerintahkan Jaksa Agung Tirtawinata memperbaiki kalimat dari segi hukum. Tapi Nasution mesti menunggu persetujuan sidang kabinet, yang baru digelar menjelang tengah malam. Sebelum sidang dimulai, Panglima Besar Jenderal Sudirman datang. Nasution menceritakan dalam bukunya, Sekretaris Negara Pringgodigdo membacakan konsep keputusan presiden tersebut. Hanya Menteri Luar Negeri H Agus Salim yang berbicara. “Kalau sudah begini, tentulah jadi tugas tentara,” tulis Nasution, mengutip Agus Salim.
Menurut Poeze, semua yang hadir di sidang kabinet sepakat menyimpulkan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan. Tragedi Madiun tercuplik dalam buku Poeze berjudul Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949. Dalam bab De PKI in actie, opstand of affaire?, Poeze melukiskan, sidang kabinet cuma butuh beberapa menit buat merestui rencana Nasution. Sudirman mendapat wewenang melaksanakan keputusan tadi.
Atas dukungan itu, Nasution melaporkan persiapan operasi kepada Sudirman. Panglima Besar menyetujuinya. Ia meminta Nasution dan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade X, melaporkan perkembangan keesokan paginya. Lewat tengah malam, Nasution bergerak. Kekuatan bersenjata Front Demokrasi Rakyat di Yogyakarta dilucuti. Tokoh yang menghadiri konferensi Serikat Buruh Kereta Api ditahan. Hampir 200 simpatisan serta tokoh PKI ditangkap. Di antaranya Alimin, Djoko Sudjono, Abdoelmadjid, Tan Ling Djie, Sakirman, dan Siauw Giok Tjan.
Semua pers yang berafiliasi ke Front Demokrasi Rakyat, seperti Buruh, Revolusioner, Suara Ibu Kota, Patriot, dan Bintang Merah, dilarang terbit. Percetakannya disegel. Wartawannya ditangkap. Poster dan spanduk Front Demokrasi dibersihkan. Sebagai gantinya, ditempel plakat yang berbunyi: “Kita hanya mengakui pemerintah Sukarno-Hatta.” Menjelang fajar, operasi itu kelar.
Nasution melaporkan hasilnya kepada Sudirman. Keesokan harinya digelar sidang Dewan Siasat Militer. Panglima Besar Sudirman lalu mengambil keputusan. Dia mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur. Ia mengirim Brigade II Siliwangi, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin, guna merebut kembali Madiun. Sedangkan Letnan Kolonel Koesno Oetomo memimpin Brigade I Siliwangi buat merebut Purwodadi, Blora, Pati, dan Kudus. Malam harinya, keputusan itu disiarkan Sudirman lewat Radio Republik Indonesia di Yogyakarta.
Di mata Poeze, penangkapan itu bukti bahwa gerakan di Madiun tidak dipersiapkan dengan matang. “Tidak ada petunjuk agar tokoh PKI di Yogyakarta pergi meninggalkan kota itu,” katanya. Para tokoh yang ditangkap itu juga mengaku tidak tahu-menahu ihwal aksi di Madiun. “Saya tidak tahu apa yang dituduhkan kepada kami,” kata Gondopratomo, sekretaris pertama Serikat Buruh Kereta Api, seperti dikutip dalam makalahnya berjudul “Kejadian-kejadian Penting Menjelang Peristiwa Madiun dan Jatuhnya Republik Indonesia ke Dalam Jebakan Neokolim”.
Makalah tadi disampaikan Gondo dalam sarasehan Peristiwa Madiun 1948 di Amsterdam, Belanda, delapan tahun lalu. Gondo mengaku ditangkap pada 18 September pagi, sebelum sidang kabinet digelar. “Pukul dua pagi kami ditangkap, lalu dibawa ke Benteng Vredenburg,” katanya. Paginya, ia dibawa ke gedung Normaal School. Dua hari kemudian, ia baru tahu bahwa ia dikenai tuduhan hendak mendirikan Negara Soviet di Madiun.
Tuduhan itu dinilai Gondo tidak masuk akal. “Kalau akan diadakan pemberontakan, kenapa pengurus Serikat Buruh Kereta Api Madiun datang ke Yogyakarta?” katanya. Di kota itu, Serikat Buruh Kereta Api tengah menyelenggarakan konferensi membahas “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Delegasi Serikat Buruh dari berbagai daerah datang ke sana.
Menurut Gondo, penangkapan itu cuma akal-akalan pemerintahan Hatta, yang ketika itu menempati posisi wakil presiden, perdana menteri, sekaligus menteri pertahanan. “Mereka sudah lama mempersiapkan penangkapan,” katanya. Kelompok kiri menuduh penangkapan dilakukan buat merebut simpati Amerika Serikat, agar negara itu menekan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Proklamasi Dini di Madiun
“Madiun sudah bangkit
Revolusi sudah dikobarkan
Kaum buruh sudah melucuti polisi dan tentara Republik
Pemerintahan buruh dan tani yang baru sudah dibentuk”
Melalui Radio Gelora Pemuda dan Radio Republik Indonesia, pidato Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia Soemarsono memecah keheningan pagi di Kota Madiun, Jawa Timur, pada 18 September 1948. Suasana mencekam merasuk hingga ke sudut-sudut kota. Pasukan Soemarsono menguasai semua gedung vital dan kantor pemerintahan. Mereka melucuti tentara dan polisi.
Soemarsono menyatakan gerakan itu upaya membela diri. Maraknya penculikan terhadap tokoh Partai Komunis Indonesia di Yogyakarta dan Solo telah menjalar ke Madiun. “Apalagi ketika itu berkeliaran pasukan gelap dengan lencana tengkorak,” katanya dalam perbincangan dengan Tempo, Oktober lalu.
Dua hari sebelum peristiwa itu, Soemarsono bertemu dengan Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri untuk melaporkan kondisi Madiun yang semakin genting. Mendapat laporan itu, Musso dan Amir kompak menjawab, “Bertindak! Lucuti saja pasukan yang menculik itu.”
Menjelang siang, Madiun bergerak pulih. Seluruh kota telah berada dalam penguasaan pemuda PKI. Keadaan ini, kata Soemarsono, harus dilaporkan ke pemerintah pusat di Yogyakarta. Namun tak satu pun pejabat Madiun yang berani melaporkan. Terjadi perdebatan sengit di antara petinggi militer PKI. “Semua saling lempar,” kata Soemarsono. Samadikun, penguasa sipil tertinggi di Madiun, sedang ke luar kota dan wakilnya, Sidarto, terbaring sakit.
Komandan Teritorial Madiun Letnan Kolonel Sumantri juga menolak. Dia malah meminta Soemarsono yang mengirimkan laporan ke Yogyakarta. “Saya bukan orang pemerintah,” Soemarsono menolak. Akhirnya diputuskan meminta Wali Kota Madiun, Purbo, mengirimkan laporan kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta. Namun Purbo juga sedang terbaring sakit.
Lalu muncullah Supardi, wakil wali kota yang baru saja diangkat. Dia mengatakan sanggup mengirimkan laporan itu. “Asalkan dengan persetujuan komandan teritorial,” katanya, seperti diceritakan Soemarsono. Semua sepakat, termasuk para bupati yang telah menyatakan mendukung PKI.
Hari itu juga Supardi mengirim telegram ke Yogyakarta, menjelaskan pelucutan senjata batalion Siliwangi dan Mobrig oleh Brigade 29. Supardi juga menyampaikan keadaan Madiun aman terkendali. “Berhubung kepergian kepala daerah, untuk sementara pimpinan pemerintahan daerah kami pegang. Minta instruksi lebih lanjut.” Demikian laporan Supardi, yang menyebut dirinya wakil Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Madiun.
Hingga menjelang petang, tak ada balasan dari Yogya. Esoknya, menjelang malam, “jawaban” itu akhirnya datang juga. Tidak lewat telegram, tapi melalui gelombang Radio Republik Indonesia di Yogyakarta. Dengan berapi-api Presiden Sukarno menyampaikan pidato menanggapi peristiwa di Madiun.
Sukarno mengatakan telah terjadi upaya kup oleh PKI di Madiun. Dia memberikan dua pilihan kepada rakyat: ikut Musso dengan PKI atau ikut Sukarno-Hatta. “Negara kita mau dihancurkan. Mari basmi bersama pengacau-pengacau itu,” Sukarno berseru.
Hanya berselang tiga jam, melalui Radio Gelora Pemuda, Musso membalas pidato Sukarno. Musso menyatakan Sukarno-Hatta hendak menjual Indonesia kepada imperialis Amerika. “Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga daerah-daerah lain akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis itu,” katanya.
Musso bersama petinggi Front Demokrasi Rakyat mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah Madiun. Para pejabat pemerintah, dari bupati sampai lurah yang propemerintah, digantikan kader PKI.
Musso kemudian melantik Soemarsono sebagai gubernur militer dan Kolonel Djoko Soedjono menjadi komandan pasukan PKI. Alasannya, pemerintahan baru ini dibentuk untuk melawan kekuatan militer. Adapun Supardi, karena dinilai berani melapor ke pemerintah pusat, diangkat menjadi residen.
Front Nasional Daerah Madiun menguasai lima kabupaten: Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Pacitan. Hari itu bupati diganti dengan kader PKI. Wilayahnya semakin luas dengan bergabungnya Wonogiri dan Sukoharjo.
Hatta mengecam tindakan Musso. Dalam pidatonya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 20 September 1949, dia mengatakan gerakan PKI itu sebagai upaya merobohkan pemerintahan Republik Indonesia dengan kudeta. “Kemudian mendirikan pemerintahan Soviet,” katanya. Sejarawan Harry A. Poeze memberikan penilaian yang sama. “Itu upaya mereka menjadikan Musso sebagai presiden,” katanya.
Bertahun-tahun kemudian, para tokoh PKI berkukuh menolak dituding melakukan pemberontakan di Madiun. “Alangkah mencari-carinya orang yang menuduh PKI merobohkan Republik Indonesia,” kata D.N. Aidit dalam pembelaannya berjudul Menggugat Peristiwa Madiun, yang dibacakan di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 11 Februari 1957.
Bantahan serupa datang dari Soemarsono. Menurut dia, kalau memberontak, PKI pasti sudah melakukan penyerangan. “Ini tidak,” katanya.
Situasi Madiun-Yogyakarta terus memanas. Pada akhir September 1948, lewat Radio Gelora Pemuda, PKI membantah tudingan Hatta. Lewat Supardi, PKI meminta upaya perdamaian dengan pemerintah Sukarno-Hatta. “Karena pemerintahan lokal di Madiun merupakan bagian dari Republik Indonesia,” kata Supardi, seperti dikutip dalam buku Himawan Soetanto yang berjudul Rebut Kembali Madiun.
Abdoel Moetholib, yang belakangan menggantikan Supardi, melakukan langkah yang sama. Dia mengumumkan daerah-daerah yang sebelumnya diduduki PKI telah kembali dilepaskan. Agar lebih meyakinkan, Moetholib melakukan penggantian bupati di Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.
Upaya itu sia-sia. Sukarno telanjur menunjuk Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengambil langkah tegas guna merebut kembali Madiun. Sepuluh batalion tentara pemerintah menyerbu Madiun.
Kota yang dikelilingi pegunungan itu dikepung dari berbagai penjuru. Petinggi PKI terdesak. Pada 28 September, Musso, Amir Sjarifoeddin, dan Soemarsono hengkang meninggalkan Madiun. “Kami terjepit,” kata Soemarsono.
Hatta Kambing Hitam Madiun
Asvi Warman Adam
Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Dalam alam sejarah yang diajarkan semasa Orde Baru, Peristiwa Madiun 19 September 1948 merupakan pemberontakan PKI yang disertai dengan pembantaian terhadap para kiai. Namun kini dipertanyakan apakah peristiwa itu merupakan pemberontakan yang bersifat nasional atau hanya perlawanan lokal (apakah coup d’etat atau coup de ville). Tentang pembunuhan terhadap pemuka Islam, hal serupa terjadi pada orang-orang kiri yang dituduh terlibat seperti disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh Roeslan Abdulgani (Casper Schuuring, Roeslan Abdulgani Tokoh Segala Zaman, 2002).
“Di sebuah gedung sekolah ditawan 43 orang komunis dan diputuskan siapa di antara mereka akan dihukum mati. Seorang letnan memohon kesediaan saya untuk hadir dalam pelaksanaan tembak mati tersebut. Dari jumlah 43 itu, lima belas orang dihukum mati dan lima di antaranya benar-benar ditembak di depan liang kubur yang sudah tersedia…. Ketika malam harinya kembali ke Madiun, saya menangis. Saya tidak pernah menangis begitu keras.” Hal yang sama menimpa Amir Sjarifoeddin dan sepuluh pemimpin teras kelompok komunis pada 19 Desember 1948 tengah malam di Desa Ngaliyan, Solo.
Pada era reformasi telah terbit berbagai buku tandingan yang memberikan penjelasan dan interpretasi berbeda mengenai Peristiwa Madiun 1948. Namun, dalam orasi atau buku-buku yang ditulis oleh kelompok kiri, Hatta selalu dijadikan target serangan. Aidit menuduh Hatta telah melakukan provokasi. Ini dikaitkan dengan “red drive proposal” berupa konsep untuk membasmi komunisme yang dikemukakan dalam pertemuan di Sarangan, Jawa Timur. Namun apakah betul ada “Pertemuan Sarangan” itu dan sesungguhnya apa isi pertemuan tersebut? Dalam hal ini satu-satunya yang sering dirujuk adalah buku Boroboedoer, sebuah kisah perjalanan yang ditulis oleh Roger Vailland. Ia lebih dikenal sebagai novelis Prancis ketimbang sebagai sejarawan. Jadi buku itu diragukan kesahihannya.
Dalam Harian Rakjat, 14 September 1953, dimuat pernyataan Politbiro CC PKI tentang Peristiwa Madiun 1948. D.N. Aidit kemudian diajukan ke pengadilan dengan tuduhan menghina dan menyerang kehormatan Wakil Presiden Republik Indonesia M. Hatta. Dalam pernyataan tersebut terdapat kata-kata “provokasi”, “keganasan”, “berlumuran darah”, dan seterusnya. Aidit menjelaskan bahwa provokasi itu berawal dari pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto, Komandan Divisi IV TNI, Juli 1948, yang dianggap sebagai orang yang menolak rasionalisasi tentara yang digariskan Hatta. Selanjutnya penculikan terhadap dua orang anggota PKI, 1 September 1948, yang dilakukan aparat pemerintah. Pada 7 September 1948, terjadi penculikan terhadap lima perwira TNI yang beraliran kiri. Semua peristiwa inilah yang menyebabkan terjadi konflik antara tentara Siliwangi dan Panembahan Senopati di Surakarta. Ketegangan ini menjalar ke Madiun dengan dilucutinya pasukan Siliwangi oleh Brigade 29 pada 18 September 1948.
Pada 19 September 1948, Hatta dengan segera meminta Badan Pekerja KNIP mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya selama tiga bulan (saja). Undang-undang yang disahkan pada 20 September 1948 itu-hanya terdiri atas satu pasal-memberikan kekuasaan penuh (plein pouvoir) kepada presiden. Maka dalam tempo dua minggu dilakukan penumpasan terhadap gerakan yang dianggap melawan pemerintah tersebut. Sementara itu, di pihak lain, Belanda, yang memperkirakan tentara Indonesia sudah sangat lemah, setelah bersusah payah mengatasi krisis Madiun, memutuskan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 untuk menghancurkan Republik Indonesia.
Tuduhan bahwa Hatta menyebabkan provokasi karena program rasionalisasi yang dijalankannya tentu perlu diklarifikasi ulang. Pada saat itu terdapat sedikit persenjataan dan lebih dari 400 ribu tentara yang terdiri atas tentara reguler dan laskar yang hendak diciutkan menjadi 60 ribu orang. Tentu dengan tujuan agar lebih efektif, patokan Hatta adalah satu senjata untuk empat prajurit. Hatta menyadari bahwa kebijakan itu menimbulkan dampak psikologis karena bisa menimbulkan kesan “habis manis sepah dibuang”, lalu kedua, siapa yang dikeluarkan dan siapa yang dipertahankan tentu menjadi isu sentral yang terkait pula dengan kepentingan partai politik yang menggarap tentara.
Ir Setiadi Reksoprodjo (yang baru meninggal beberapa bulan lalu pada usia 89 tahun), Menteri Penerangan dalam kabinet Amir Sjarifoeddin pada 1947, memberikan kesaksian 13 halaman tulisan tangan kepada saya, menjelaskan jasa Amir dalam mengefektifkan angkatan bersenjata Indonesia. Sejak November 1945 sampai Januari 1948, Amir berturut-turut menjadi Menteri Keamanan Rakyat/Menteri Pertahanan. Pada awal kemerdekaan, unsur tentara terdiri atas berbagai kelompok terlatih (eks didikan Belanda/Jepang) dan laskar. Dalam masa transisi, menurut Amir, diperlukan Tentara Masyarakat.
Amir juga berpendapat RI hanya bisa bersandar pada perjuangan kekuatan rakyat, bukan pada tentara konvensional. Tentara RI haruslah tentara rakyat, tidak boleh bersifat elitis, karena bila terpisah dari rakyat, mereka tidak berdaya apa-apa. Kelaskaran memiliki tradisi akrab dengan rakyat, tapi memang kedisiplinannya dalam berorganisasi harus ditingkatkan. Ini berbeda dengan tentara didikan Belanda dan Jepang, yang umumnya kurang mengerti perlunya keterlibatan rakyat.ntuk itu, Amir mendirikan badan pendidikan politik tentara untuk menjembatani perbedaan antara kelaskaran dan tentara reguler. Skema itu sudah mulai dijalankan, tapi belum berlangsung lama karena agresi Belanda. Bahkan kemudian Amir digantikan Hatta sebagai perdana menteri.
Perbedaan antara pandangan Hatta dan Amir Sjarifoeddin mengenai pengelolaan tentara tinggal perdebatan sejarah. Yang jelas, telah terjadi ketegangan dan konflik sesama kelompok tentara di samping persaingan keras partai politik. Tapi apakah program rasionalisasi tentara (yang disebut Re-Ra oleh Nasution) yang dilakukan Hatta yang menjadi penyebab Peristiwa Madiun masih perlu dikaji lebih lanjut. Jadi tudingan “provokasi Hatta” itu lebih bersifat tendensius. Menjadi pertanyaan pula kenapa Hatta yang dituduh, dan bukan Sukarno. Ketika Aidit berpidato “Menggugat Peristiwa Madiun” di DPR, 11 Februari 1957, Hatta sudah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Tentara yang dipimpin Jenderal Nasution sudah merapat kepada Presiden Sukarno dan hubungan ini kian mesra pada saat dan setelah meletus PRRI/Permesta. Maka, mulai 1960-an, kekuasaan terpusat pada aktor segitiga: Sukarno di atas dan PKI-Tentara di sudut kiri-kanan bawah. Hatta, yang sudah kehilangan kekuasaan, dengan mudah dijadikan kambing hitam.
Warisan Kebencian
Anthony Reid (Revolusi Nasional Indonesia, 1996) mengatakan bahwa respons pemerintah terhadap Peristiwa Madiun tidak sulit dimengerti. Negosiasi seperti yang diusulkan Sudirman mungkin dapat menyelamatkan banyak nyawa, tapi dengan ongkos keberhasilan propaganda Belanda bahwa Republik Indonesia tidak berdaya terhadap komunis dan kepastian dukungan Amerika Serikat bagi Belanda untuk melakukan intervensi. Sukarno-Hatta memilih bertindak tegas terhadap kelompok oposisi kiri tersebut.
Masih menurut Reid, Peristiwa Madiun penting tidak hanya karena jumlah korban yang besar (konon, 8.000 orang PKI dibunuh oleh TNI menurut tuduhan pihak Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebaliknya banyak pula orang dari kalangan pemuka Islam yang tewas), tapi juga karena warisan kebencian yang ditinggalkan antara kelompok kanan (santri) dan kiri (abangan). Bagi Sukarno-Hatta, Peristiwa Madiun secara gamblang merupakan pemutusan gagasan revolusi nasional dengan revolusi sosial. Pada 1945, keduanya seakan tak terpisahkan. Namun, setelah Peristiwa Madiun 1948, revolusi sosial itu tertunda sementara waktu. Walaupun arah revolusi belum tuntas ditentukan, ia telah dibanting ke kanan.
Menurut Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (1997), perdebatan apakah peristiwa Madiun merupakan pemberontakan (versi resmi) atau provokasi pemerintah Hatta (versi kiri) tidak menjawab persoalan mendasar. Yang terjadi sebetulnya adalah ketegangan di tengah masyarakat (di Jawa) dalam revolusi nasional karena harapan-harapan yang tidak terpenuhi dan kesulitan ekonomi yang membawa frustrasi. Ini memunculkan radikalisme yang terus meningkat ibarat perlombaan mobil di lereng gunung yang makin lama makin menyempit. Suatu saat roda yang berputar itu bersinggungan, bergesekan, dan bertubrukan, maka timbul percikan api yang membakar. Masalah ini akan lebih jelas bila dilacak secara multidisiplin, yaitu dari aspek sosial-politik (perubahan masyarakat setelah 1942), ekonomi (kehancuran dan perkembangan ekonomi setelah perang), dan budaya (pertentangan Islam-nasionalis, Sunda versus Jawa, melalui konflik Divisi Siliwangi-Panembahan Senopati).
Dendam itu dilanjutkan dengan fatwa Masyumi, Desember 1954, yang menyatakan bahwa komunisme itu identik dengan ateisme. Sebelumnya, M. Isa Anshary telah membentuk Front Anti Komunisme di Jawa Barat. Keluarnya fatwa ini bisa dilihat dalam konteks persaingan antara Masyumi dan PKI dalam menghadapi Pemilu 1955. Benih kebencian itu perlu dihilangkan dengan mengkaji sejarah secara jernih. Buku pelajaran sejarah perlu ditulis secara cerdas dengan perspektif baru.
Lunglai di Rawa Klambu
Rambut gondrong, jenggot berjuntai tak terurus. Mukanya pucat seperti kehilangan darah. Berhari-hari di rawa dengan bekal minim membuat Amir Sjarifoeddin lunglai dan terserang disentri. Bersama rombongannya, dia sulit keluar dari rawa di hutan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah, yang terkenal angker. Mereka dikepung tentara yang menyeru supaya Amir menyerah. Amir menjawab hanya akan berpasrah kepada Pasukan Divisi Panembahan Senopati.
Permintaan Amir dipenuhi. Pasukan Senopati menjemput. Amir berjalan terpincang. Bekas perdana menteri itu hanya memakai piyama, sarung, dan tak bersepatu. Kacamatanya masih bagus. Pipa cangklong, yang biasanya tak pernah terpisahkan dengannya, absen. Siang itu, 29 November 1948, akhir pengembaraan Amir yang diburu TNI karena peristiwa Madiun.
Amir menyerah bersama tokoh PKI Soeripno, serta empat pengawal. Kuda Amir sebelumnya sudah tertinggal, dan anjing kesayangannya, Sora (sering dipanggil Zero), ditemukan tentara pada 26 November. “Dalam pernyataan pertamanya, Amir mengatakan akan kembali ke Solo dan Yogya dengan menyamar sebagai pedagang,” kata Harry A. Poeze, dalam bukunya, PKI Bergerak: Pemberontakan atau Peristiwa?.
Dua hari sebelum Amir ditangkap, tentara melancarkan operasi pembersihan di rawa Godong, dekat Nawangan, Purwodadi, Jawa Tengah. Pasukan Kala Hitam, yang dipimpin Kemal Idris, menurunkan Seksi I Siradz dan Seksi III Sarmada. Ketika berpatroli, tentara menemukan beberapa orang di semak. Sewaktu dipanggil, mereka berpura-pura mati. Tentara mengancam akan menembak sehingga semua mengangkat tangan.
Mereka mengaku dari desa dan menjadi tawanan PKI. Pasukan Kala Hitam tak percaya pengakuan itu, soalnya mereka memiliki pistol. Komandan Peleton Suratman, seperti ditulis Tempo pada 1976, melihat mereka putus asa, kelelahan, dan kelaparan. Bagaimanapun, mereka seperti orang kota yang tak terbiasa berkeliaran di hutan dan rawa. “Pertempuran di hutan berawa-rawa itu sulit sekali. Pandangan terhalang oleh pepohonan,” kata Suratman.
Setelah dibawa ke pos terdekat, baru diketahui bahwa orang yang mengaku penduduk desa itu pentolan Front Demokrasi Rakyat/PKI, yakni Djoko Soedjono, Maroeto Daroesman, dan Sardjono. Dalam pemeriksaan, Djoko Soedjono mengatakan Amir berada beberapa ratus meter dari tempat dia. Tujuan mereka bukan menyeberang ke daerah pendudukan Belanda, melainkan bergabung dengan pasukan PKI yang dikira masih aktif.
Pengembaraan Amir dan pentolan PKI lainnya di rawa-rawa mulai dilakukan setelah Madiun direbut tentara. Musso, Amir, dan pucuk pimpinan yang lain buru-buru mengundurkan diri ke Dungus dan Ngebel, Ponorogo. Mereka dikawal pasukan tentara merah dan ribuan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) bersenjata lengkap berikut kaum ibu dan anak-anak.
Mereka membawa berjuta ORI (Oeang Republik Indonesia), berkarung beras, mesin tulis, mobil, amunisi, kambing, ayam, bendi, kuda. Sebagian perbekalan itu berceceran di jalan. Dokumen tertulis saja yang tak pernah tertinggal. Mereka berjalan kaki, sebagian berkuda. Dalam buku Revolusi Agustus, Soemarsono bercerita semua perbekalan itu akan dipakai untuk persiapan setelah masuk wilayah kekuasaan Belanda.
Sampai di Balong, Ponorogo, Musso berselisih dengan Amir. Surat kabar Sin Po menggambarkan konflik kedua pemimpin itu karena perebutan kekuasaan di Madiun. Sumber lain menyebutkan Musso dan Amir berbeda pendapat tentang basis penyerangan baru sesudah Madiun jatuh. Musso menghendaki ke selatan, sedangkan Amir ke utara.
Muhammad Dimyati, dalam bukunya, Sedjarah Perdjuangan Indonesia, melontarkan pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Musso seorang diri? Mengapa ia tak mendapat pengawalan bersenjata, padahal ada ribuan prajurit merah aktif? Dimyati menulis: “Masih mendjadi soal gelap jang tidak mudah diterangkan.”
Musso dikawal beberapa orang yang bertualang ke selatan dan terdampar di pegunungan sekitar Ponorogo. Dia tewas dalam penyergapan pada 31 Oktober 1948. Sedangkan induk pasukan Amir meneruskan perjalanan. Mereka menyusuri jalan menuju Tegalombo ke Pacitan. Pasukan Amir bertemu dan bergabung dengan pasukan Ahmad Jadau di Purwantoro.
Atas saran Jadau, mereka bergerak ke utara. Iring-iringan lebih dari 2.000 orang itu dikawal Pesindo di depan, belakang, lambung kiri dan kanan. Poeze mengatakan rombongan itu meliputi pengikut PKI bersenjata, kader, dan keluarga. Ada juga orang desa yang dipaksa ikut sehingga jumlahnya membengkak terus dalam setiap perjalanan.
Tentara mengepung PKI di segitiga Ponorogo-Pacitan-Wonogiri, tapi sama sekali bukan pagar betis kuat. Pasukan TNI tak bisa menutup semua akses sehingga tentara merah berhasil lari ke utara. Tapi long march menggerus sebagian kekuatan PKI. Dalam pertempuran di Purwantoro, PKI kehilangan tim Abdoel Moetolib yang terpisah dari pasukan induk.
Pasukan Amir sampai di Wirosari dan masih memiliki 800 personel bersenjata dan seribu anggota keluarga. Bekas Panglima Siliwangi, Himawan Soetanto, mengatakan pasukan Amir menuju ke daerah Belanda karena ada kemungkinan selamat dan terus hidup dibanding berada di daerah Republik.
Dua bulan pasukan PKI melakukan long march. Rombongan akhirnya sampai di daerah rawa di hutan Klambu, Grobogan, sekitar 50 kilometer dari Madiun. Kekuatan mereka tinggal sekitar lima ratus orang karena serangan tentara Indonesia.
Dalam serangan 26-29 November di kawasan Klambu, sekitar 1.200 tentara PKI menyerahkan diri, termasuk Amir dan pemimpin lainnya yang menanti eksekusi. Gubernur Militer Madiun PKI Soemarsono selamat karena berhasil masuk ke daerah pendudukan Belanda yang digariskan dalam Perjanjian Renville.
Kabar kedatangan mereka ditunggu ribuan warga Yogyakarta. Amir, Soeripno, dan Harjono dibawa ke Yogyakarta dengan kereta api pada 5 Desember 1948. Dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Soe Hoek Gie menulis kereta sengaja dikosongkan untuk keperluan itu. Wartawan Antara mewawancarai mereka di kereta. Amir diam sambil membaca Rome and Juliet karya William Shakespeare. Dua lainnya mengatakan pasrah sejak meninggalkan Madiun.
Amir dan kawan-kawan ditahan berdasarkan aturan yang menetapkan bahwa gubernur militer berwenang menjebloskan tahanan politik atau militer ke penjara. Ada 560 tahanan yang diatur dengan tata cara dan disiplin militer di Yogyakarta. Tahanan dibagi ke dalam tiga kategori, yakni mereka yang sekadar ikut-ikutan, terlibat langsung, dan para pemimpin.
Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerbu pedalaman Republik atau dikenal dengan Agresi Militer II. Tentara Indonesia harus siap perang gerilya karena sulit menandingi kekuatan Belanda. Sejumlah tahanan dibebaskan dan dipersenjatai. Pembebasan itu berlanjut sampai Januari 1949. Sekitar 35 ribu tahanan politik dibebaskan untuk menangkis Belanda.
Pembebasan itu tak berlaku bagi Amir dan sepuluh orang lainnya yang dibawa ke Desa Ngalihan, sebelah timur Solo. Mereka adalah Amir, Soeripno, Maroeto, Sardjono, Oei Gee Hwat, Harjono, Djoko Soedjono, Sukarno, Katamhadi, Ronomarsono, dan D. Mangkoe.
D.N. Aidit, seperti dikutip Lembaga Sedjarah PKI, melukiskan peristiwa di Ngalihan pada 1953. Larut malam di Ngalihan. Sekitar dua puluh orang sibuk menggali kuburan. Kepada Amir diperlihatkan surat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto mengenai eksekusi pemimpin PKI itu.
Amir dan kawannya bercakap dengan tentara. Soeripno sempat menulis surat untuk istrinya. Mereka lalu menyanyikan Indonesia Raja dan Internasionale. “Setelah selesai bernjanji Bung Amir menjerukan: bersatulah kaum buruh seluruh dunia! Aku mati untukmu!” Amir ditembak lebih dulu.
Isu eksekusi Amir beredar beberapa hari kemudian di Jakarta. Namun pemerintah menolak memberikan pembenaran. Penjara Amir kosong, tapi keberadaannya tak terlacak. Wartawan Rosihan Anwar mengatakan, sejumlah media, termasuk Pedoman, luput memberitakan peristiwa malam berdarah di Ngalihan.
Pada Januari 1949, Sin Po menulis bahwa Amir dan Maroeto dihukum mati. Wawancara Sin Po dengan Ketua Mahkamah Militer Tinggi Koesoemaatmadja menyebutkan pemimpin PKI dibawa ke Solo dan diserahkan ke Gubernur Militer Gatot Subroto ketika penyerangan Belanda.
Sesudah penyerahan kedaulatan pada 1950, peristiwa eksekusi itu mencuat lagi. Istri Harjono dan Djoko Soedjono menerima kabar bahwa suami mereka dieksekusi pada 19 Desember 1948. Pada 15-18 November 1950, kuburan digali dan jenazah diidentifikasi. Pemakaman kembali pada 19 November disaksikan sepuluh ribu pengunjung.
Di Ngalihan, makam tak bernisan itu kini tak terawat. Penduduk setempat hanya mengenalnya sebagai kuburan PKI. Ngalihan menjadi semacam penutup episode Madiun yang menelan korban ribuan orang. Aidit menyebutkan, operasi tentara dalam Peristiwa Madiun menyebabkan sepuluh ribu buruh dan tani tewas.
Tiga Dilepas Demi Revolusi
Rumah tingkat dua di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, itu berbagi tembok dengan dinding parit. Luasnya sekitar 30 meter persegi, dengan tegel abu-abu yang kusam. Dindingnya cuma semen yang belum dipelur. Itulah bekas rumah Paulus al-Gadri dan istrinya, Paulina Sukarti. Keduanya, yang baru bebas dari tahanan politik era Soeharto pada 1980-an, menikah pada 1985. Kini rumah itu ditempati para tukang servis jok dan sofa.
Tetangga sekitar mengenalnya sebagai Ibu Karti yang jago matematika dan Pak Gadri yang pandai bahasa Inggris. Rusminah, pemilik warung di pojok jalan ke gang rumah tersebut, menilai tetangganya itu sebagai dermawan. “Suka kasih uang jajan ke anak saya, yang sudah dianggap cucunya sendiri,” ujar nya.
Kedua tokoh ini bukanlah pribadi sembarangan. Paulina Sukarti pernah menjadi aktivis Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia, salah satu organisasi massa Partai Komunis Indonesia. Adapun Paulus al-Gadri, lulusan Akademi Hukum Militer, adalah oditur berpangkat kapten Angkatan Darat di Hakim Militer Jakarta. Jabatan penting terakhir yang dipegangnya adalah Kepala Rumah Penjara Tentara di Cimahi pada 1952.
“Orangnya pintar tapi lurus banget, kayak si Kabayan,” kata Uchi Kowati, keponakan Sukarti, tentang pamannya. Karena sifatnya yang lempeng dan dermawan itu, Uchi awalnya tak percaya Al-Gadri adalah putra Musso. Apalagi tantenya berkata, “Halah, anak Musso kok kayak begitu.”
Saat membangun rumah, Al-Gadri sering mempersilakan tukang batunya bekerja setengah hari. Apalagi saat dia lihat para pekerja sudah letih. Tinggal Sukarti yang geleng-geleng kepala.
Lain waktu, Al-Gadri yang justru marah kepada istrinya. Baginya, ilmu harus dibagi. Memberikan les sama dengan menjual ilmu kepada orang lain. Sukarti memberikan les fisika, kimia, dan matematika kepada anak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk mencari nafkah. Setelah diterangkan, les yang dia berikan tak sama dengan menjual ilmu, Al-Gadri paham. Ia pun memberikan les bahasa Inggris bagi beberapa guru. “Dia cuma dibayar Rp 5.000,” kata Uchi.
Uchi baru percaya pamannya ini bukan sembarang orang saat Al-Gadri serius mencari kerabat dan keturunan Musso di Rusia sejak 1990. Sampai tahun 2000, ketika Al-Gadri meninggal di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia karena kanker, rekan-rekannya di Eropa masih membantunya mencari keluarga Musso di Rusia.
Al-Gadri menganggap Uchi putri sendiri sehingga mempercayakan surat-surat penting dan barang berharga miliknya. Termasuk barang mewah pada zamannya: arloji emas kebanggaan sang paman, yang rusak dan tak terawat, tapi selalu saja dipakai. Aneh, dia kan enggak kerja, ngapain pakai arloji, pikir Uchi. Ia menyarankan agar arloji itu dijual, tapi ditolak Al-Gadri. Karena, “Ini sudah menemani saya sejak saya masih di luar penjara,” katanya kepada Uchi.
Pada Agustus 1948, sepulang dari Cekoslovakia, Musso berkeliling ke daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyebarkan “Jalan Baru”-nya. Di kantor PKI di Bintaran Wetan, Yogyakarta, Musso bertemu dengan putranya, Margono, dan istrinya (sejauh ini Tempo belum mendapatkan namanya), yang ditinggalnya saat ke Rusia pada 1926.
Saat itu Musso memberikan arloji kepada Margono. Arloji pada masa itu merupakan barang mewah. Tapi, sebagai pejabat di Komunis Internasional, Musso bisa mendapatkannya. Jabatan terakhirnya Ketua Biro Asia dan Timur Tengah. Dan itulah pertemuan pertama dan terakhir Musso dengan putranya. Dia berpesan, “Setelah kamu pulang, kamu mesti siap berjuang demi revolusi.”
Soerjono alias Pak Kasur-suami pencipta lagu anak Ibu Kasur yang menjadi anggota Gerakan Kepanduan Indonesia, menulis peristiwa itu dalam catatannya yang berjudul “On Musso’s Return” yang diterjemahkan Benedict Anderson.
Uchi tak tahu cerita tentang Margono sampai arloji itu muncul. “Bisa jadi arloji yang sama, bagus banget, tapi tak dirawat.” Yang pasti, selain dari arloji, Uchi melihat ciri fisik Al-Gadri mirip postur Musso, hitam dan tinggi besar. Ia menduga Al-Gadri nama samaran, karena merupakan nama marga di Timur Tengah. Paulus nama baptisnya sebagai Katolik, keyakinan yang dia pilih setelah sering bertemu dengan pendeta.
Al-Gadri pernah bercerita sejak kecil dia diasuh Murdoko, petani di Kediri. Nama Musso lebih baik menghilang di Kediri karena sejak 1924, sudah menjadi buron Belanda. “Dia cuma tersenyum kalau ditanya nama aslinya,” ujar Uchi.
Menurut Smaun Oetomo dari Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru, nama para anggota PKI sudah diincar. “Karena komunis di dunia ingin menghantam penjajahan, langsung konfrontasi,” ujar bekas Ketua Buruh Kereta Api itu.
Ada pula kisah Mariana Winarni, putri Al-Gadri. Menurut Mariana, ibunya, Samsirah, bercerai dengan ayahnya, karena belakangan tahu ayahnya keturunan Musso. “Setelah itu, Ibu tak pernah cerita apa pun soal ini, apalagi soal Kakek (Musso),” ujarnya saat ditemui di kediamannya di Magetan.
Waktu menikah, dia memakai nama Mohamad al-Gadri, kelahiran Surabaya, 2 April 1926. Tapi, ketika Al-Gadri ditangkap, lingkungan di Magetan tahu dia keturunan Musso.
Samsirah hanya tahu suaminya tentara bergelar sarjana hukum militer. Latar belakangnya terbongkar ketika diciduk Resimen Para Komando Angkatan Darat. Dia dituduh memimpin pasukan mengambil alih Radio Republik Indonesia dalam peristiwa Gerakan 30 September.
Al-Gadri menilai operasi itu cuma jebakan untuk menjerat dia. Ketika datang, sudah banyak senjata terkumpul, tapi dia dituduh yang menaruh. Uchi tak tahu pasti kapan tentara mengetahui Al-Gadri putra Musso. “Mungkin sebelum 1965, makanya dijebak.” Dia bebas setelah 16 tahun mendekam di penjara Salemba dan Cipinang, lebih singkat daripada vonis Mahkamah Militer Luar Biasa selama 20 tahun.
Sekeluar dari penjara, Al-Gadri tak pernah bertemu dengan anaknya, Mariana, dan kakak Mariana, Winarno. Ketika keluar dari penjara, dia ditampung seorang pendeta di rumahnya, di bilangan Pakubuwono, Kebayoran Baru. Di sana Samsirah menemui Al-Gadri setelah menerima surat Al-Gadri yang menyatakan dia ingin bertemu istri dan anaknya. Tapi Samsirah datang tanpa putra-putrinya itu. Dia datang hanya untuk mengakhiri hubungan.
Meski karier militernya yang cemerlang jatuh dan dicerai karena keturunan Musso, Al-Gadri mengaku tak kecewa. “Saya bangga jadi anak Musso,” ujarnya kepada Uchi.
Al-Gadri akhirnya bertemu dengan Mariana dan Winarno kala dia koma di rumah sakit. “Kami cuma sempat pegangan tangan dengan Bapak, besoknya Bapak meninggal,” ujar Mariana. Bersama anak dan cucunya, Mariana kini tinggal di rumah kontrakan seluas 70 meter persegi, tak jauh dari rumah dia dan ibunya, Samsirah. Sebagai penyambung hidup, Mariana bekerja sebagai penjahit. Kakaknya, Winarno, meninggal pada 2002.
Sambutan kepada tetamu dari Indonesia di rumah Profesor R. Intojo selalu meriah. Maklum, flat sastrawan Pujangga Baru di Moskow, Rusia, itu jadi rendezvous orang Indonesia. “Karena kami keluarga nondiplomat, sering banyak yang berkunjung tanpa sungkan.” Para tamu selalu suka masakan Indonesia buatan ibunya, seperti ayam goreng dan semur daging.
Intojo dikirim Presiden Sukarno pada 1956, sebagai janjinya kepada Uni Soviet mengirim pakar mengajar bahasa dan sastra Indonesia ke Negeri Beruang Merah.
Vidji Utami Intojo, putri sulung sang profesor, masih ingat perawakan Musman Pavlov dan Sunar Musso yang tinggi dan berkulit cokelat seperti Musso. “Seperti orang bule sepekan di Asia,” kata eks pengajar bahasa Indonesia di Institut Hubungan Internasional itu.
Mereka sering ke rumahnya yang cuma empat kilometer di Jalan Leninsky Prospekt. Bangunan flat di jalan ini untuk kalangan kelas menengah ke atas. Luas rata-rata flat sekitar 80 meter persegi. Intojo memperkenalkan Musman dan Sunar kepada Ami-sapaan Vidji Utami -yang kala itu masih 11 tahun, sebagai anak Musso, orang yang lama tinggal di Uni Soviet. “Saya tahu Musso dari buku sejarah Uni Soviet,” kata Ami.
Sunar, anak perempuan Musso dari pernikahan pertamanya di Rusia, lulusan Jurusan Bahasa Indonesia Institut Ketimuran Moskow. Musman, anak dari pernikahan Musso yang kedua dengan Lydia Pavlova-Musman memakai nama belakang keluarga ibunya-kala itu berumur 18 tahun, dan mahasiswa baru Institut Bahasa Asing Moskow.
Di Rusia, Sunar menjadi aktivis seperti ayahnya. Dia anggota Gerakan Buruh Internasional di Moskow. Hingga akhir 1960, meski sakit-sakitan, dia masih aktif di sana. Pada 1970, Sunar meninggal tanpa sempat berkeluarga. Adapun Musman bekerja sebagai penerjemah bahasa Jerman dan Rusia. Ia meninggal tiga tahun lalu dan meninggalkan seorang putri.
Meski hidup tanpa sorotan publik di Moskow dan sedikit yang kenal mereka sebagai keturunan Musso, Ami melihat mereka bangga dengan ayahnya. Mereka tahu ayahnya sedikit dari orang Indonesia yang menjadi petinggi di Uni Soviet. “Waktu kecil mereka tahu banyak tokoh politik seluruh dunia bergabung dengan Komintern,” ujar lulusan Sejarah Kesenian Universitas Lomonosov, Moskow, itu.
Djalan Baru yang Kandas
Suatu malam, pertengahan 1950. Embun menyergap tubuh Soemarsono ketika ia bergegas keluar dari sebuah rumah di Sentiong, Gang Tengah, Matraman, Jakarta. Bekas Gubernur Militer Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun itu rupanya diusir Alimin, Koordinator Departemen Agitasi Propaganda Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC PKI). Pertemuan di rumah anak Alimin itu ditandai dengan perdebatan keras. “Alimin tak suka kesetiaan saya pada Djalan Baru kawan Musso,” kisah Soemarsono kepada Tempo, awal September lalu.
Soemarsono, yang ketika itu berusia 28 tahun, datang sembunyi-sembunyi. Tentara sedang mencarinya karena dia pelaku peristiwa yang disebut-sebut sebagai pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948. “Alimin menguji, strategi apa yang akan saya pakai jika saya menjadi pimpinan PKI,” kata Soemarsono.
Alimin ternyata tak sepaham dengan Musso. Untuk membuktikan Musso keliru, Alimin menceritakan sebuah mimpinya. Suatu malam Jumat Kliwon, dia berjalan kaki menerabas hutan dari Solo ke Semarang. Di tengah hutan, karena sangat lelah, Pono, salah satu tokoh PKI pada masa itu, menggendong dia. Langkah mereka terhenti ketika terdengar bunyi menggelegar dari dalam tanah yang merekah. Lalu suara Musso keras terdengar, “Min, aku salah.” Alimin menafsirkan mimpinya sebagai penyesalan Musso karena gagal memimpin PKI.
Soemarsono tertawa mendengar tamsil itu. Alimin marah dan mengusir tamunya. Soemarsono punya alasan membantah Alimin. “Orang komunis kok percaya yang gaib. Dulu dia juga mau ditonjok Musso karena kurang radikal, suka main perempuan.”
Kejadian malam hari di Sentiong itu merupakan potret krisis kepemimpinan di tubuh PKI setelah Peristiwa Madiun. Pemimpin partai dan ribuan kader dibunuh tentara Republik dan rakyat antikomunis. Penjara dipenuhi pengikut paham komunis. Mereka yang lolos tiarap, seraya mencari hidup dengan menyamar.
Padahal tujuh belas hari sebelum aksi Madiun, PKI masih kelihatan utuh. Politbiro CC PKI baru terbentuk. Sekretariat umum dijabat Musso, Maroeto Daroesman, Tan Ling Djie, dan Ngadiman. Departemen Buruh dikendalikan Harjono, Setiadjid, Djoko Sudjono, Abdul Madjib, dan Achmad Sumadi. Urusan tani dipegang A. Tjokronegoro, D.N. Aidit, dan Sutrisno. Kepemudaan diurusi Wikana dan Soeripno. Amir Sjarifoeddin memimpin Departemen Pertahanan. Agitasi dan Propaganda diurus Alimin, Lukman, dan Sardjono. Departemen Organisasi dipegang Sudisman. Departemen Luar Negeri dikendalikan Soeripno. Perwakilan sekretariat dijabat Njoto dan bendahara diserahkan kepada Ruskak. Djalan Baru yang ditulis Musso di Yogyakarta pada Agustus 1948 menjadi pedoman partai. Tapi semua berantakan begitu cepat setelah Peristiwa Madiun. Alimin, Tan Ling Djie, Wikana, Sudisman, Aidit, Njoto, dan Lukman hanya sebagian kecil dari pentolan partai yang selamat.
PKI mendapat “napas baru” pada pertengahan 1949. Debat panjang dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akhirnya memutuskan memberikan hak hidup kepada PKI. Partai palu-arit itu diminta turut mempertahankan Republik yang hendak diacak-acak Belanda lagi. Argumen yang berkembang di KNIP: di negara-negara Barat partai komunis dibiarkan hidup, maka di Indonesia juga tak boleh dibinasakan. “Spiritnya berjuang bersama-sama,” kata Rosihan Anwar, wartawan koran Siasat, yang meliput sidang-sidang KNIP.
Surat keputusan pemberian maaf kepada PKI ditandatangani Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo, 7 September 1949. Isinya: pemerintah tidak akan menuntut PKI, tapi mereka tak boleh terlibat tindakan kriminal. Secarik kertas itu menjadi “tiket” bagi para kamerad partai komunis untuk keluar dari gua-gua persembunyian.
PKI pun menobatkan Alimin sebagai pemimpin sementara. Pemimpin baru ini punya konsep perjuangan yang berbeda dengan Musso. Alimin berpikiran PKI hanya perlu hidup sebagai partai kecil tapi dengan anggota yang militan dan menyebar ke semua organisasi massa. Kemudian semua anggota dan organisasi massa itu diikat dalam sebuah front untuk meneruskan revolusi. Konsep Alimin ini bertolak belakang dengan Djalan Baru Musso yang radikal dan terbuka. Kaum muda, seperti Aidit, Lukman, dan Njoto, cenderung mengikuti “kawan” Musso.
Pengikut garis Musso ini kemudian mendirikan open office di Jakarta bersama Sudisman. Sisa Politbiro CC PKI lama, seperti Wikana dan Tan Ling Djie, tak dilibatkan. Hanya Alimin yang dijadikan formatur. Soemarsono juga ditinggalkan karena dinilai terlalu yakin pada perjuangan bersenjata. “Tak ada yang berani melawan Aidit. Semua yes man saja. Saya lebih senior tapi sulit berdebat dengan Aidit. Saya lebih suka mengalah,” ujar Soemarsono mengenang suasana ketika itu.
Kongres PKI pada 1951 menunjuk Aidit-Lukman-Njoto menjadi ketua satu, dua, dan tiga Politbiro CC PKI. Kaum tua diberi jabatan tak penting. Belakangan, Alimin mundur dan digantikan Sakirman. Sejak kongres inilah perjuangan lewat parlemen dan akselerasi merebut hati rakyat digulirkan PKI.
Ketika Presiden Sukarno melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat, 15 Februari 1950, PKI mendapatkan jatah kursi. Saat itu PKI membuka dialog dengan unsur agama dan nasionalis, seperti Partai Sarekat Islam Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Murba.
Pada 15 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Eksistensi PKI semakin kuat, kedudukannya di parlemen kian kukuh. Larissa M. Efimova, dalam bukunya, Dari Moskow ke Madiun, mencatat pada waktu itu Uni Soviet tidak mengirim ucapan selamat atas terbentuknya NKRI. Pertukaran nota dan telegram soal hubungan Soviet-Indonesia juga tak ada. Tapi PKI tak ambil pusing.
Sikap kritis kepada pemerintah terus dikembangkan. Dalam sidang parlemen pada Oktober 1951, PKI menolak Konferensi Meja Bundar. PKI ikut serta mendukung mosi Hadikusumo yang mengkritik lemahnya pemerintah. Gara-gara mosi itu, Perdana Menteri Natsir akhirnya mundur. Penandatanganan mutual security act pemerintah Indonesia-Amerika juga tak luput dari serangan PKI. Partai palu-arit beranggapan pakta itu akan menjadi legitimasi untuk menguras sumber daya alam Indonesia.
Dalam kongres pada 1954 di Malang-ketika, konon, disediakan kursi kosong untuk Stalin, pemimpin komunis Soviet-PKI mengamanatkan partai untuk menguasai desa, kota, dan tentara. Petani dan buruh diperintahkan menjadi perwakilan untuk meluaskan pengaruh di desa dan kota. Semua organisasi onderbouw PKI didorong menjadi alat propaganda partai.
Hasilnya tak sia-sia. PKI menjadi pemenang keempat Pemilihan Umum 1955 dengan meraup 16,4 persen-di bawah PNI yang meraih 22,3 persen, Masyumi dengan 20,9 persen, dan Nahdlatul Ulama yang merebut 18,4 persen. Resep keberhasilan PKI, menurut Harry Albert Poeze, Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara, adalah kepemimpinan Aidit-Lukman-Njoto yang berhasil memulihkan kepercayaan rakyat dari trauma terhadap PKI.
Dalam bukunya, Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949, Poeze melukiskan peran trio itu sebagai pembersih noda Peristiwa Madiun. “Pembersihan” itu, misalnya, dilakukan lewat koran Bintang Merah yang menulis peringatan dua tahun peristiwa Madiun. “Media yang diasuh trio Aidit-Lukman-Njoto itu menyebut Musso tidak memberontak atau bercita-cita mendirikan negara Soviet,” kata Poeze. Tahun berikutnya, Bintang Merah memuat artikel “Tiga Tahun Provokasi Madiun”, yang ditulis Mirajadi-nama samaran Sudisman. Departemen Agitasi Propaganda PKI tak ketinggalan dalam proyek ini dengan menerbitkan buku putih Peristiwa Madiun pada 1953. Kata pengantarnya ditulis Aidit. Dalam resolusinya, Aidit menuding Sukarno-Hatta-Natsir provokatif dan kejam menyikapi Peristiwa Madiun. Gara-gara resolusi itu, Aidit diajukan ke meja hijau 14 Oktober 1954, dengan tuduhan menghina Wakil Presiden Hatta.
Di persidangan Aidit membuat gempar dengan menyebut Musso komunis patriotis. Ruang sidang geger. Hakim sampai memukul-mukulkan palu untuk minta pengunjung kembali tenang. Dukungan untuk membebaskan Aidit mengalir deras. “Empat ribu surat dan telegram yang diorganisir PKI dikirim ke pengadilan,” ujar Poeze. Tapi hakim tetap memvonis Aidit tiga bulan penjara bersyarat dengan enam bulan masa percobaan.
Menjelang Pemilu 1955, pidato pembelaan Aidit diterbitkan kembali, tapi dirampas penegak hukum. Pemerintah melarang peringatan Peristiwa Madiun. Dalam naskah pidatonya di sidang DPR pada 11 Februari 1957, Aidit kembali membela Musso. Alhasil, “PKI tak kenal lelah untuk membantah tuduhan coup d’etat Madiun,” kata Harry Poeze. “Tapi saya percaya rencana itu ada.”
Djalan Baru Musso kandas di Madiun. Dan kita tak pernah menyaksikan apa yang ditulis sebagai kalimat terakhir Djalan Baru menjadi kenyataan: “Kaum Bolsjewik Indonesia akan dapat merebut benteng yang terancam bahaya, yaitu benteng Indonesia Merdeka”. Toh, konsep itu-seperti juga “induk”-nya, yakni komunisme-niscaya tak pernah mati.
Jalan Berliku Tuan Mussotte
Bonnie Triyana
Sejarawan dan Pemimpin Redaksi Majalah Historia Online
Matu Mona menggambarkan Paul Mussotte, nama bagi karakter Musso dalam roman Patjar Merah Indonesia, sebagai orang terkenal, pemberani, dan jago berpidato. Menurut Soemarsono, tokoh pemuda Angkatan ’45, Musso dikenalnya sebagai tokoh yang teguh memegang prinsip betapapun nyawa taruhannya. Indonesianis Ruth McVey menempatkan Musso, selain Alimin, sebagai tokoh penting di balik kebangkitan PKI pada 1920-an. Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (2005) menyamakan Musso dengan Haji Misbach, yang “senang amuk-amukan” dan sedikit nekat.
Nama Musso diliputi kisah kelam pemberontakan yang tiada berkesudahan. Dia, bersama sepuluh pemimpin PKI lainnya, menggagas perlawanan rakyat terhadap otoritas kolonial pada 1926. Kemudian, pada 1948, ia dipersangkakan sebagai orang yang hendak mendirikan Republik Soviet-Indonesia di Madiun dan mengkudeta pemerintahan Sukarno-Hatta. Apakah Musso tak punya kisah lain dalam sejarah Indonesia?
Sebagaimana aktivis politik di zaman itu, Musso membagi kesetiaannya kepada Insulinde, Sarekat Islam, dan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. Bersama Alimin, Musso ditangkap oleh pemerintah kolonial atas tuduhan terlibat insiden Afdeling-B pada 1919. Insiden itu dipicu oleh resistensi Haji Hasan dari Cimareme, Garut, yang menolak membayar pajak padi kepada pemerintah.
Sarekat Islam mengalami radikalisasi sebagai konsekuensi masuknya unsur-unsur kiri ke organisasi itu dan mendadak jadi incaran pemerintah. Sederet tokoh Sarekat Islam, yang sudah terpecah dua, SI Merah dan SI Putih, ditangkapi pemerintah kolonial. Musso pun ditekan untuk mengakui peran H.O.S. Tjokroaminoto dalam insiden Afdeling-B. Namun, berbeda dengan Alimin yang mengakui bahwa dia berbohong demi menyelamatkan Tjokroaminoto, Musso berkeras menyatakan di depan pengadilan bahwa pemimpin karismatis rakyat Jawa itu sama sekali tak terlibat, kendati pada akhirnya Tjokroaminoto tetap ditangkap.
Sikap Musso terhadap Belanda di kemudian hari terpengaruh oleh perlakuan yang kurang menyenangkan yang didapatnya dalam penjara kolonial. Pengalaman traumatis itu menumbuhkan kesumat di dalam hatinya kepada Belanda. Pada 1923, dia dan Alimin dibebaskan dari penjara. Mereka lantas memegang kendali partai dan mulai memainkan peran penting dalam memperbesar jaringan partai dan pengaruhnya terhadap rakyat. Alimin aktif mengorganisasi pelaut dan buruh pelabuhan di Tanjung Priok, sementara Musso mereorganisasi PKI Batavia (Michael C. Williams, 2003). Peran Musso sangat strategis, terlebih apabila melihat kenyataan bahwa daerah garapannya berada di wilayah yang bukan basis komunis.
Di beberapa daerah, PKI mendapat resistensi karena dianggap kontradiktif dengan ajaran Islam, tak terkecuali di Banten, yang terkenal dengan ortodoksinya. Namun, di bawah kendali Alimin-Musso, daerah yang dikenal puritan itu justru menjadi sentra pendukung partai yang dominan. Bahkan PKI Banten mengubah pandangannya terhadap Islam yang semula netral menjadi hiper-religius. Hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan tegas terhadap Puradisastra, ketua PKI setempat yang menunjukkan sikap kurang simpatik dengan meminum secangkir kopi sebelum azan magrib tiba saat bulan puasa.
Dalam jangka waktu setahun setelah pembebasannya, duet Musso-Alimin berhasil meluaskan jangkauan pengaruh PKI di Jawa Barat. Pertemuan demi pertemuan diselenggarakan secara rahasia demi menghindari tindakan otoritas kolonial yang semakin represif. Setelah kongres istimewa di Kotagede, Yogyakarta, pada 1924, partai telah mantap memilih aksi bersenjata dalam rangka revolusi. Kongres juga sepakat membangun organisasi ilegal dan keputusan itu disetujui dalam rapat pimpinan PKI pada Maret 1925. Salah satu pertemuan terpenting adalah Konferensi Prambanan 25 Desember 1925 yang menghasilkan keputusan berontak melawan Belanda. Musso hadir dalam pertemuan itu.
Sejarah mencatat pemberontakan berlangsung pada November 1926 di Banten dan Januari 1927 di Silungkang, Sumatera Barat. Musso tak berada di Indonesia saat kejadian itu meletus. Ia telah pergi ke Singapura dan lantas ke Moskow guna mencari dukungan Soviet. Tapi api revolusi yang berkobar padam sebelum waktunya. Dugaan Tan Malaka benar, kondisi obyektif sebagai prasyarat sebuah revolusi belum terlalu matang untuk dipetik. Otoritas kolonial pun menghabisi PKI sekali pukul. Namun dari sini bisa dilihat bagaimana kerja Musso cum suis membesarkan partai: ratusan ribu orang menyerahkan kartu anggotanya saat pemerintah Belanda meminta mereka menyerahkan diri.
Musso baru datang kembali ke Indonesia pada 1935 dan langsung menuju Surabaya. Di sana ia memulai upaya menyatukan serpihan kekuatan PKI yang tercerai-berai dengan mendirikan CC PKI dan menunjuk sendiri orang-orang yang menjalankan partai secara ilegal, yakni Pamudji, Azis, Sukajat, dan Djoko Soedjono. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai PKI 1935, merujuk ke tahun kedatangan Musso. Tokoh muda Amir Sjarifoeddin, yang kelak memegang peran penting di Republik yang masih belia, termasuk kader binaan Musso. Ketatnya pengawasan dinas rahasia pemerintah kolonial dan “karena faktor kecerobohan… konsolidasi PKI itu terbongkar oleh Belanda,” tulis Sok Hok Gie (2005: 25).
Pekerjaan Musso menyatukan gerakan PKI bawah tanah ini harus dinilai sebagai suatu jasa yang cukup besar dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap fasisme Jepang. Seperti diketahui, selang tujuh tahun setelah kedatangannya, Jepang menduduki Indonesia. Kelompok yang paling aktif dalam menentang fasisme itu adalah PKI ilegal bentukan Musso. Sejumlah sabotase dan perlawanan seperti yang terjadi di Singaparna dan Indramayu erat kaitannya dengan kelompok ini. Beberapa orang dari mereka tertangkap, bahkan dieksekusi oleh Jepang. Sebagian, seperti Widarta cs, meneruskan perlawanan di bawah tanah terhadap Jepang.
Musso baru datang lagi ke Indonesia pada 11 Agustus 1948 dengan menyamar sebagai sekretaris Soeripno, utusan pemuda dalam International Union of Student di Praha yang berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Kepulangannya ke Indonesia kembali membawa misi menyatukan gerakan kiri yang terserak karena konflik internal dan tindakan represi Jepang. Menurut Gie, kedatangan Musso disambut dengan tangan terbuka bagaikan “juru selamat” di tengah suasana frustrasi dan kebingungan PKI yang membutuhkan pemimpin baru.
Partai Komunis Indonesia memang masih tetap dalam identitasnya yang samar. Partai ini masih ilegal dan tak sempat menghadirkan diri sebagai partai legal segera setelah Indonesia merdeka. Padahal, melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X/1945, berbagai kelompok politik di Indonesia diperbolehkan mendirikan partai politik. Aktivis PKI yang masih terus di bawah itu terlalu sibuk dengan saling klaim siapa yang paling sah. Alih-alih bersatu di bawah panji palu-arit, mereka saling cakar. Widarta merasa dirinya paling sah, demikian pula Sardjono, Mr Yusuf, dan Amir Sjarifoeddin.
Keadaan itu mendapat reaksi keras dari Musso. Ia mengatakan bahwa tidak dimengertinya keadaan politik setelah proklamasi Indonesia membuat PKI tetap dalam jubah penyamarannya di bawah tanah. Padahal, menurut Musso, itulah saat yang tepat bagi PKI untuk memunculkan diri ke hadapan rakyat dalam wajah yang legal. Musso menganjurkan PKI kembali sebagai partai pelopor kelas buruh; PKI kembali ke tradisi sebelum dan selama Perang Dunia II dan meraih hegemoni sebagai pemimpin revolusi nasional Indonesia.
Setiba di Yogyakarta, Musso melontarkan gagasan supaya partai-partai politik yang berbeda menyatukan diri dalam Front Nasional untuk menghadapi Belanda. Ia mengadakan koreksi total terhadap gerakan PKI dan koreksinya itu dikenal sebagai Djalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso agaknya mafhum bahwa persatuan mutlak dibutuhkan agar revolusi Indonesia tidak salah jalan. Dia mengutip Friedrich Engels bahwa revolusi akan gagal jika tidak diadakan perubahan yang radikal, sementara revolusi Indonesia tidak melakukan itu. Kesalahan kedua menurut Musso terjadi karena pemimpin revolusi tidak berasal dari golongan buruh sebagai kelompok yang paling revolusioner (Gie, 2005: 226).
Tapi, menurut Soeryana dalam catatannya tentang kedatangan Musso, upaya Musso menyatukan kekuatan kiri tak berlangsung mulus karena ulah Musso sendiri yang membawa isu Trotskyisme ke dalam negeri. Kesalahan itu menyebabkan Musso kehilangan kesempatan untuk merekrut kader-kader terbaik dari Partai Murba dan Angkatan Komunis Muda (Akoma). Perseteruan dengan golongan Tan Malaka yang sering distigmatisasi sebagai Trotskyis itu sudah bermula pada 1926. Padahal ada beberapa kesamaan cara pandang yang mereka miliki dalam soal menghadapi Belanda: mereka berdua tak setuju jalan perundingan dan memilih merebut perjuangan dengan cara bersenjata; mereka berdua sama-sama khawatir bahwa Republik yang masih muda akan jatuh ke pangkuan penjajahan dalam bentuknya yang baru.
Konflik itulah yang agaknya dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah Hatta untuk bisa mengontrol gerakan Musso. Kelompok Tan Malaka yang dipenjara karena insiden 3 Juli 1946 pun dilepaskan untuk mengimbangi aksi Musso. Pergesekan itu semakin panas dan berujung pada Peristiwa Madiun, September 1948. Sukarno pun menyampaikan pidato “Pilih Musso atau Sukarno-Hatta?”. Musso jadi buruan. Pada 31 Oktober 1948, dia tewas dalam sebuah baku tembak dengan TNI di daerah Ponorogo.
Setelah itu, nama Musso tenggelam dalam tuduhan sebagai pemberontak nista yang meletupkan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia pada 1948. Sejarah hanya merekam kisah hitam hidupnya tanpa pernah melihat sisi lain dari perannya sebagai aktivis politik yang menentang fasisme, imperialisme, dan kolonialisme. Sama seperti tokoh lain yang terselip hitam di antara putihnya, Musso punya jasa untuk bangsa ini.
Tag :
Sejarah

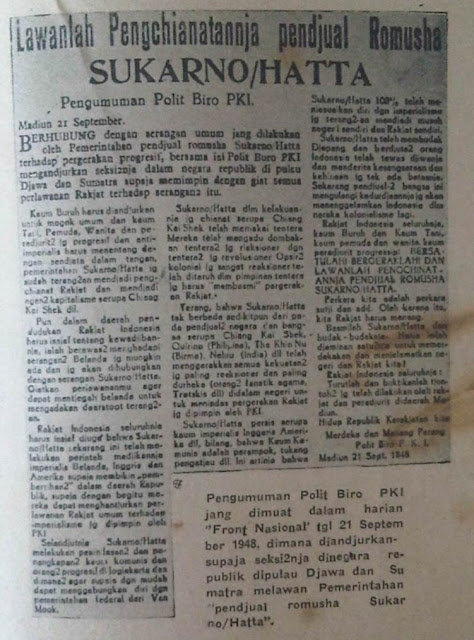



1 Komentar untuk "Kisah Munawar Musso Dan Pemberontakan PKI 1948"
Jemboute Brokoli, ini tulisan dari siapa.